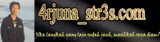Wali dan Mahar dalam Nikah
Oleh Masyithah Mardhatillah (07530003)
A. Wali Nikah
‘Kebijakan’ hukum fiqh yang mewajibkan adanya wali dalam suatu pernikahan pada pihak wanita dan tidak pada pihak pria memang terkesan bias gender. Namun agaknya, penyimpulan yang terburu-buru ini bisa diminimalisir dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut. Misalnya dengan mengingat hikmah di balik adanya syarat wali dalam satu pernikahan. Syarat ini menjadikan pernikahan (yang dalam Al-Qur`an dibahasakan dengan mitsaqan ghalidza) dilakukan dengan penuh pertimbangan, tidak `asal jadi dan asal suka`, dan disertai persetujuan beberapa pihak terkait. Kehadiran wali juga menandakan adanya restu dari orang tua kedua mempelai.
Oleh Masyithah Mardhatillah (07530003)
A. Wali Nikah
‘Kebijakan’ hukum fiqh yang mewajibkan adanya wali dalam suatu pernikahan pada pihak wanita dan tidak pada pihak pria memang terkesan bias gender. Namun agaknya, penyimpulan yang terburu-buru ini bisa diminimalisir dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut. Misalnya dengan mengingat hikmah di balik adanya syarat wali dalam satu pernikahan. Syarat ini menjadikan pernikahan (yang dalam Al-Qur`an dibahasakan dengan mitsaqan ghalidza) dilakukan dengan penuh pertimbangan, tidak `asal jadi dan asal suka`, dan disertai persetujuan beberapa pihak terkait. Kehadiran wali juga menandakan adanya restu dari orang tua kedua mempelai.
Karena itulah, hal ini juga menjadi alasan mengapa hakim menempati hirarki alternatif terakhir yang baru boleh dipakai jika wali seorang perempuan benar-benar berhalangan. Kehadiran wali dalam akad nikah selain merupakan suatu perwujudan restu, juga memiliki makna yang cukup substantif. Wali seorang perempuan menyerahkan tanggung jawab dan sepenuh kepercayaannya pada mempelai laki-laki yang akan menjadi pemimpin putrinya. Dengan demikian, wali kedua belah pihak memang seyogyanya hadir dan menyaksikan akad nikah. Masing-masing wali tersebut hadir untuk memberikan restu, meski wali seorang perempuan memiliki peran yang –katakanlah- lebih penting.
Secara etis, kehadiran wali dalam akad nikah ini tidak hanya menjadi formalitas. Untuk memasuki kehidupan baru, seorang anak sudah sewajarnya meminta restu dan do`a dari orang tua yang telah membesarkannya. Hal ini diharapkan dapat mempermudah kedua mempelai dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebab itulah dalam sebuah hadist yang cukup populer, Rasulullah menegaskan, لا نكاح الا بولي (tidak ada pernikahan –yang sah- tanpa adanya seorng wali). Saya beranggapan ada dimensi syariat, barokah, dan etika dalam hadist Nabi tersebut.
Selain itu, adanya kewajiban wali dalam Islam juga memiliki akar historisitas tersendiri. Pada masa jahiliyah, wali berkuasa sepenuhnya atas keberadaan seorang perempuan, utamanya dalam masalah pernikahan. Seorang wali berhak mengatur segala urusan yang berhubungan dengan pernikahan anaknya, dari urusan memilih calon mempelai hingga kepemilikan mas kawin. Seorang wanita tidak memiliki kesempatan untuk memilih calon pasangannya dan ia pun tidak berhak mengelola mas kawin pernikahannya.
Islam sebagai syari`at yang menyempurnakan dan merupakan paripurna dari segala syariat sebelumnya kemudian mengadakan perubahan substansial dalam hal ini. Syariat Muhammad masih menetapkan adanya wali sebagai syarat sah suatu pernikahan, namun dengan mengubah beberapa hal. Semisal adanya perintah untuk menanyakan persetujuan calon mempelai wanita dan kepemilikan mas kawin yang sepenuhnya diserahkan pada wanita.
Adapun kualifikasi seorang wali adalah status sebagai keluarga dekat yang memiliki hubungan darah. Semisal ayah, kakek, saudara kandung, dan paman. Alternatif kedua adalah keluarga yang juga masih memiliki hubungan darah akan tetapi sudah cukup jauh dari silsilah keluarga. Sedangkan alternatif terakhir adala hakim. Hirarki tersebut ditarik dari kesimpulan umum mengingat ada perbedaan pendapat yang cukup tajam di kalangan fuqaha`.[1] Alternatif yang disebutkan dalam hirarki tersebut berlaku jika golongan wali yang berada dalam hirarki di atasnya berhalangan hadir karena beberapa sebab.
Bias gender agaknya juga tampak dalam kualifikasi wali nikah ini. Wanita tidak boleh menjadi wali. Barangkali, larangan Rasulullah ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan bangsa Arab saat itu yang masih meng-underestimate-kan kaum wanita. Hal ini misalnya tampak dalam jumlah wanita yang menjadi saksi suatu proses peradilan yang berbanding 1–2 dengan laki-laki. Dalam salah satu bedah buku, Sahiron Syamsuddin menegaskan bahwa hal tersebut dilatarbelakangi dengan keadaan sebelumnya yang sama sekali tidak diberikan hak dan kesepmatan memberikan persaksian.[2] Sederhananya, saat itu wanita dikhawatirkan belum berpengalaman dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang persaksian. Sehingga, ia butuh seorang teman untuk belajar dan berproses bersama.
Saya rasa ada sinkronitas antara kasus persakian dengan kualifikasi wali ini. Namun, upaya untuk meng-goalkan kualifikasi perempuan dalam wali nikah agaknya masih memerlukan proses yang cukup panjang.
B. Mahar (Mas Kawin)
Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa pada masa Jahiliyah, mahar seorang wanita diserahkan pada walinya, sehingga ia memiliki keterbatasan (atau bahkan tidak memiliki) hak untuk memberdayakan mas kawinnya tersebut. Dalam hal ini, Islam merespon dengan teknik taghyir, yakni menetapkan pemberian mas kawin dalam suatu pernikahan namun dengan beberapa perubahan yang cukup esensial. Tengoklah misalnya surat An-Nisa` ayat 4 berikut;
(#qè?#uäur uä!$¡ÏiY9$# £`ÍkÉJ»s%߉¹ \'s#øtÏU 4 bÎ*sù tû÷ùÏÛ öNä3s9 `tã &äóÓx« çm÷ZÏiB $T¡øÿtR çnqè=ä3sù $\«ÿ‹ÏZyd $\«ÿƒÍ£D ÇÍÈ
Ayat ini cukup menggambarkan bahwa Islam menghendaki terangkatnya derajat kaum wanita, dari yang semula tidak sama sekali berhak pada mas kawin pernikahannya menuju derajat di mana wanita memiliki hak sepenuhnya terhadap barang yang menjadi mas kawin pernikahannya. Ayat ini juga menggambarkan fleksibilitas pendayagunaan mahar, yakni kebolehan seorang suami untuk (ikut serta) mengelola mas kawin tersebut dengan idzin dan restu dari isti sebagai pemilik sah mas kawin tersebut.
Terkait dengan substansi mahar, saya beranggapan bahwa mas kawin merupakan suatu pemberian yang diberikan calon suami kepada calon istrinya. Hal ini dilakukan untuk menyenangkan dan menghibur hati calon istri yang barangkali gelisah untuk memulai sebuah kehidupan baru. Saya lebih mendukung fuqaha` yang mengatakan bahwa mahar bukanlah ‘harga tukar’ suami pada isteri yang telah menyerahkan jiwa raganya. Sebab pada dasarnya, pernikahan bukanlah suatu lembaga untuk mengangungkan budaya patriarkhi yang menempatkan perempuan pada posisi kedua. Setidaknya, hal ini bisa disimpulkan jika melihat ayat yang mengatakan bahwa isteri adalah pakaiain (pelengkap) bagi suami dan begitu juga sebaliknya. Hubungan suami-istri bukanlah hubungan yang subordinatif, namun lebih merupakan hubungan yang komplementif.
Hal yang juga menguatkan asumsi saya atas hal ini adalah adanya sebuah hadist yang mengatakan bahwa wanita terbaik dalam hal ini adalah mereka yang menentukan mas kawin yang ringan dan tidak memberatkan bagi suami. Praktik ini menampakkan adanya toleransi dan rasa pengertian dari pihak wanita kepada keadaan pihak pria, utamanya dalam masalah ekonomi. Akan tetapi, jika pihak suami memiliki kesanggupan finansial untuk memberikan mas kawin yang cukup berharga, maka dalam hal ini, saya rasa istri sah-sah saja menetapkan mahar yang juga cukup ‘mahal’.
Adapun teknis-teknis seputar mas kawin ini, seperti tidak adanya batas minimal mas kawin dan kebolehan tidak memberikan dan atau menyebutkan mas kawin dalam akad nikah, serta konsep mahr mitsl, dalam hemat saya erat kaitannya dengan tujuan dasar pemberian mas kawin ini. Yakni memberikan kebahagiaan material kepada pihak wanita tanpa harus memberatkan finansial pihak lelaki. Sejarah mencatat bahwa pada masa Rasulullah, beliau sama sekali tidak memberikan kualifikasi mahar yang memberatkan pihak lelaki. Para sahabat bahkan disuruh menikah dengan mahar yang sangat sederhana, semisal baju perang, dua sandal, masuk Islam, bahkan dengan membaca sebuah surat dalam Al-Qur`an.
Dengan demikian, bisa dikatakan tidak ada kualifikasi khusus tentang mas kawin dalam suatu pernikahan. Syarat mas kawin hanyalah sesuatu yang bermanfaat. Dan ukuran manfaat dan tidaknya ini bergantung pada selera dan pandangan masing-masing. Kita lihat misalnya dewasa ini, beberapa kalangan terkadang memilih mas kawin yang aneh dan antik, semisal jumlah uang yang sama dengan tanggal pernikahan, dan sebagainya.
Saya kemudian berkesimpulan bahwa beberapa event saat Nabi ngotot menyuruh para sahabat untuk menikah dengan mas kawin seadanya adalah suatu isyarat pentingnya pernikahan. Dan arti penting ini tidak seharusnya terhalangi karena ukuran material dalam hal kewajiban memberikan mas kawin. Apalagi, Allah telah menjamin rizki orang-orang yang menikah. Allah Knows Best
Jogja, 7 April, 2009, 07.47.
[1]Lih. Sayyid Sabiq, Fikih Sunah terj. Moh. Thalib, (Bandung: Al-Ma`arif, 1982), hlm. 10-14.
[2]Syahiron Syamsuddin, dalam bedah buku Is Islamic Law Secular? Penerbit: Nawesea Press di Teatrikal UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 18 Maret, 2009.