Perempuan Berkalung Sorban;
Tradisionalitas dan Modernitas
Film yang diangkat dari novel karangan Abiedah el-Khaliqy ini banyak menggambarkan konflik, benturan, dan perebutan antar budaya tradisional dengan budaya modern yang berlatar kehidupan pesantren. Hal yang menjadikan film ini sedikit berbeda barangkali adalah setting yang dipilih. Perbenturan budaya modern dan budaya tradisional dalam film-film Indonesia bukanlah merupakan hal yang baru, namun demikian jika bidikan film ini adalah budaya tradisional dan budaya modern ala pesantren, maka hal yang demkian cukup menjadi alasan untuk menyebut film ini berbeda dengan yang lain.
Pesantren yang menjadi setting dalam film ini tergolong pesantren yang bercorak tradisional yang otomatis juga memuat budaya-budaya tradisional. Tema besar yang juga diusung penulis novel ini, selain benturan dua kebudayaan juga menyangkut tema kesetaraan gender. Bagaimana kemudian konsepsi tradisional dalam film ini dipertemukan dengan konsep kesetaraan gender (yang notabene merupakan salah satu wujud budaya modern) adalah adanya penggambaran marginalisasi wanita dalam ranah-ranah tertentu. Marginaliasi tersebut mendapat legitimasi dari budaya tradisional yang menggariskan kodrat wanita sebagai mahluk kelas dua yang hanya berdiam di kasur, di dapur, dan di sumur.
Metafor-metafor yang menggambarkan benturan dua konsepsi tersebut misalnya adalah saat Anisa (diperankan oleh Nasya Abigail pada masa kanak-kanak dan Revalina S. Temat pada masa dewasa) mendapat larangan keras untuk menunggang kuda, menjadi ketua kelas, dan untuk berjalan di luar area pesantren. Dalam beberapa momen ini, Annisa yang digambarkan sebagai seorang yang kritis bukannya tidak menolak. Namun demikian, ia terkalahkan oleh otoritas abi-nya (panggilan untuk ayah dalam Bahasa Arab) sebagai kepala keluarga dan pemimpin pesantren. Annisa kemudian hanya memendak keinginan-keinginannya yang dianggap aneh dan sesekali mencuri kesempatan untuk mewujudkan keinginan-keinginannya.
Puncak dari beberapa hal kurang menyenangkan pada masa kanak-kanak dan menjelang remajanya terjadi manakala ia ditinggalkan oleh teman bermain terdekat yang juga familinya, Khudori (diperankan Oka Antara) yang akan melanjutkan pendidikan. Khudori digambarkan sebagai seseorang yang selalu memahami keinginan-keinginan ‘gila’ Annisa. Selepas Aliyah, Annisa yang berkeinginan melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah harus mengurungkan niatnya sebab ia dipaksa menikah dengan anak lelaki teman ayahnya. Pernikahan Annisa dengan Syamsuddin (diperankah oleh Reza Rahadian) senyatanya juga merupakan pernikahan dua pesantren yang kental dengan nuansa kapitalisme. Secara ekonomi, orang tua Syamsuddin memiliki beberapa link potensial yang bisa dijadikan sasaran proposal untuk membesarkan pesantren Al Huda.
Sampai di sini, ada beberapa representasi budaya modern yang muncul dari pikiran (dan kemudian tindakan Annisa) yang berupaya menolak ketidakadilan yang dialaminya. Annisa menginginkan adanya kebebasan dan hak yang setara antar wanita dan lelaki. Hal ini misalnya tergambar saat Annisa mempertanyakan mengapa ayahnya melarang dirinya menunggang kuda sedangkan dua saudara lelakinya tidak mendapat teguran. Annisa kemudian juga tidak habis pikir mengapa ayahnya tidak memberi idzin dan lampu hijau baginya untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana yang didapatkan dua kakak lelakinya.
Alur cerita selanjutnya menyajikan konsepsi-konsepsi yang tidak jauh berbeda, yakni berputar di area benturan dua kebudayaan dan kesetaraan gender. Setelah menjalani pernikahan dengan Syamsuddin, sosok Annisa yang mendambakan kebebasan dan kesetaraan malah semakin menemukan keadaan yang lebih buruk dengan keadaan rumah tangga yang sama sekali tidak ia harapkan. Syamsuddin sering berlaku kasar kepadanya dan Annisa pun, dengan kekuatan fisiknya yang lemah, hanya bisa memberikan perlawanan sebisanya
Syamsuddin kemudian muncul sebagai tokoh yang amat sangat berpegang teguh pada budaya tradisional patriarki dan memandang wanita sebagai manusia kelas dua. Ia menganggap dirinya memiliki otoritas mutlak sebagai suami dan donatur terbesar pesantren milik ayah Annisa. Ia melarang Annisa melanjutkan pendidikan di bangku kuliah dengan alasan kodrat wanita tidaklah berada dalam wilayah publik, namun di wilayah domestik. Annisa pada dasarnya menentang pemahaman Syamsuddin tersebut, namun ia tidak memiliki cukup daya untuk terbebas dari kungkungan suaminya.
Pemikiran tradisionalis yang mendarah daging dalam diri Syamsuddin juga banyak dikendalikan oleh watak dan kebiasaannya yang kurang baik. Ia tidak memberikan kasih sayang yang tulus pada Annisa dan tidak pernah memberi perlakuan yang pantas. Ia melegitimasi segala tindakan –yang tidak berkeprimanusiaan tersebut—dengan konsep bahwa dalam rumah tangga, suami menjelma seorang raja dan isteri adalah budaknya.
Superioritas dan keangkuhan Syamsuddin ini pada gilirannya menggiring Annisa pada perceraian yang sangat ia inginkan. Dalam sebuah adegan yang penuh suspense, Syamsuddin menceraikan Annisa di hadapan khalayak setelah memfitnah Annisa tengah melakukan zina dengan Khudori yang saat itu telah kembali ke Indonesia. Ayah Annisa mendapat serangan jantung dalam adegan ini dan kemudian menghembuskan nafas terakhirnya.
Setelah tidak memiliki keterikatan dengan Syamsuddin, Annisa mulai mengejar ketertinggalannya dan membuka kehidupan barunya di Yogyakarta. Ia memulai pendidikan kampus, merintis karier kepenulisan, dan bekerja di sebuah LSM yang concern pada hak-hak perempuan. Dari ketiga aktivitasnya ini, Annisa berusaha mewujudkan angan-angan yang sempat ia pendam lama. Saat ini pulalah ia kembali bertemu dengan Khudori dan kemudian menikah.
Sayangnya, Annisa kembali harus berpisah dengan Khudori setelah Khudori mengalami kecelakaan lalu lintas. Di sini, representasi seorang perempuan yang ‘bisa berdiri’ tanpa topangan seorang lelaki kembali diperkuat dengan beberapa adegan yang meski menunjukkan betapa rapuhnya Annisa sepeninggal Bukhari, namun ia tetap teguh pada komitmen dan concern-nya. Terwujudnya cita-cita Annisa untuk memasyarakatkan membaca dan menulis di pesantren milik ayahnya pada ending film ini merupakan puncak dari perjuangan dan perjalanan hidupnya.
Penokohan dalam film ini cukup kuat, namun sayang, munculnya pemikiran modern dalam diri Annisa ini kurang begitu masuk akal jika mengingat bahwa ia lahir dan dibesarkan dalam lingkungan pesantren yang notabene—dalam fim tersebut—digambarkan sebagai institusi dengan kekentalan budaya tradisional. Tidak ada adegan yang paling tidak menggambarkan akses informasi Annisa kecil yang kemudian memiliki pola pikir yang berbeda dengan orang kebanyakan. Ilustrasi-ilustrasi dalam film ini justru didominasi oleh indoktrinisasi (dengan ucapan maupun perbuatan) mengenai peran wanita sebagai manusia kelas dua. Dengan ini pula, tidak berlebihan kiranya jika kemudian muncul asumsi bahwa ada beberapa hal penting dalam film ini yang terkesan dipaksakan.
Budaya tradisional yang tampak dalam film ini paling tidak direpresentasikan oleh ayah Anisa dan beberapa ustadz maupun birokrat pesantren yang masih terbaku dan terbekukan oleh doktrin-doktrin klasik yang kurang beralasan. Hal ini misalnya tampak ketika Annisa mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan ketua kelas, posisinya diganti dengan teman lelakinya yang memiliki nilai lebih rendah dibanding Annisa. Dengan mengutip suatu kandungan hadist—yang mengatakan bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin--, ustadz tersebut kemudian memutuskan bahwa jabatan ketua kelas yang sebenarnya merupakan milik Annisa digeser pada kandidat lain sebab kandidat tersebut adalah lelaki.
Representasi budaya tradisional tersebut juga banyak digambarkan dengan sikap taklid buta terhadap doktrin-doktrin budaya klasik yang memunculkan phobia hebat terhadap hal-hal baru. Hal ini misalnya terjadi saat Annisa mendapat murka ayahnya hanya karena mengunjungi bioskop dan pada saat birokrat pesantren yang membakar semua buku yang dianggap merupakan buku luar dengan kekhawatiran akan mencetak santri menjadi manusia liar.
Tidak dapat dipungkiri, pemikiran tradisional ini berkaitan erat dengan pemahaman yang –maaf—kaku terhadap ajaran agama dan konstruk sosial-budaya. Hal yang menjadi legitimasi dari semua pemikiran tersebut diperkuat dengan sikap para pendukung budaya ini yang tidak mau melihat perkembangan dan tuntutan zaman. Mereka memiliki keinginan yang kuat untuk tidak tercerabut dari ajaran agama hingga sama sekali tidak mau menerima hal-hal baru.
Benturan demi benturan dua kebudayaan memang terasa sangat kental dalam film ini, namun demikian, seringkali ada semacam ketidaktegasan skenario dalam hal ini. Jika sebelumnya film ini menggambarkan konfrontasi-konfrontasi dua kebudayaan, semisal pelarangan menunggang kuda, perintah untuk menikah dengan calon pilihan orang tua, dan pembakaran buku-buku yang dianggap liar, maka ending cerita ini justeri merusak semua konflik yang muncul sebelumnya. Asumsi ini tergambar jelas ketika beberapa birokrat pesantren –yang awalnya menentang keras beredarnya buku-buku bacaan nonpesantren-- kemudian dengan mudah menerima perpustakaan di lingkungan pondok dengan adegan yang sama sekali tidak argumentatif dan tidak logis.
06 Des, 2009
skip to main |
skip to sidebar

Sekadar nama, yang barangkali akan menjadi momentum banyak hal.. yang ingin kumulai dari entah berapa jauh dari masa ketertinggalanku akan lari dunia yang melebihi kencang hembusan badai...
Welcome to my blog, hope you enjoy reading.
Islamic Calendar
Facebook Badge
Feedjit
IT IS ME!
Blog Archive
-
▼
2009
(96)
-
▼
Desember
(10)
- Kembara akhir Semester 5 (Hohoho...)
- Lagi-lagi (Creita anak2 kelasQ)
- Abis-abisan Edisi...
- Pended Presentation (gara2 telat)
- EnglishQ jongkok
- Makalah DeprivasiQ
- Kelasku; Miniatur Dunia
- Tentang Kemukus dan…Perselingkuhan..
- Lagi-Lagi (Tugas Kelompok): Psikologi Agama; Konve...
- Gara-Gara Overbored...(Nulis by order jadi Gen-Geg...
-
▼
Desember
(10)
Labels
TemAn
Copyright 2009
serumpun KATA selumbung CERITA.
Blogger Templates by Deluxe Templates
WP Themes designed by EZwpthemes
Blogger Templates by Deluxe Templates
WP Themes designed by EZwpthemes


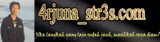
1 comMentz:
Mungkin itu Film penuh kepentingan dari Sang Sutradara(bukan Hirata) artinya ada kepentingan untuk menjelekan islam
Posting Komentar