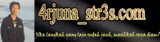Membaca dan Menulis
; Antara Tuntutan dan Pencarian
Ateilla Mirza
Membaca dan menulis adalah setali tiga uang. Semakin banyak bacaan yang dikonsumsi, maka potensi produkitivitas menulis pun akan semakin besar. Begitu juga, semakin banyak karya yang dihasilkan, maka seseorang juga akan lebih menderita haus bacaan. Idealnya demikian. Sayang, tidak semua pembaca bisa sukses menjadi pembaca yang cerdas. Pembaca yang selalu merasa semakin bodoh setiap kali mendapat pengetahuan baru. Dan tidak semua penulis bisa menemukan diri dan indentitasnya dalam tulisan. Mereka yang berupaya menuliskan apa yang sudah diolah dengan matang dalam monolog pikirannya.
; Antara Tuntutan dan Pencarian
Ateilla Mirza
Membaca dan menulis adalah setali tiga uang. Semakin banyak bacaan yang dikonsumsi, maka potensi produkitivitas menulis pun akan semakin besar. Begitu juga, semakin banyak karya yang dihasilkan, maka seseorang juga akan lebih menderita haus bacaan. Idealnya demikian. Sayang, tidak semua pembaca bisa sukses menjadi pembaca yang cerdas. Pembaca yang selalu merasa semakin bodoh setiap kali mendapat pengetahuan baru. Dan tidak semua penulis bisa menemukan diri dan indentitasnya dalam tulisan. Mereka yang berupaya menuliskan apa yang sudah diolah dengan matang dalam monolog pikirannya.
Pernyataan di atas sedikit banyak terinspirasi dari ungkapan Yudi Latief berikut, “kian banyak mencipta, kian banyak membaca; kian banyak bacaan, kian banyak hasil penciptaan"(Yudi Latif)[i]. Tidak dapat dipungkriri, membaca dan menulis –yang oleh Yudi dibahasakan dengan mencipta- adalah dua kebiasaan yang memiliki relasi simbiosis mutualisme. Kemahiran menulis akan ditunjang oleh meruahnya bahan bacaan. Dan saat suatu karya berhasil diciptakan, akan muncul pertanyaan dan kegelisahan baru yang akan mendorong seseorang untuk kembali membaca.
Dalam dunia mahasiswa, budaya membaca dan menulis merupakan tuntutan vital yang tak terbantahkan. Terlepas dari semua kesibukan dan pencarian jati diri, mahasiswa tidak bisa melepaskan diri dari dua budaya ini. Di manapun ia berkarier, apapun wadah yang menaunginya, mahasiswa tidak bisa mengukuhkan phobia pustaka dan pena. Jawabannya sederhana, sebab mahasiswa adalah simbol intelektualitas. Dan pustaka serta pena adalah medium paling utama yang tidak bisa dipisahkan dari simbol agung tersebut. Mahasiswa akan mahir memainkan pena dan cakap bersilat lidah dengan dua budaya ini.
Lalu pertanyaannya, seberapa dalamkah dua budaya tersebut telah tertanam dalam keseharian kita yang `terlanjur` disebut mahasiswa?
Memang, tidak semua mahasiswa memiliki gelar murni sebagai kutu buku yang rajin bolak-balik perpustakaan. Namun, mereka juga tidak bisa berlama-lama jauh dari buku. Sebab tuntutan silabi dan dosen tidak akan pernah henti mendekatkan mereka pada buku. Dan pada perkembangannya, romantisme dengan buku dan pustaka ini akan memunculkan dua kelompok mahasiswa, yakni mereka yang berhasil jatuh cinta pada buku dan mereka yang hanya bisa menghampiri buku saat mereka membutuhkan. Jika demikian, kita termasuk kelompok yang mana? Well, hati Anda lebih bisa menjawab sendiri.
Sayangnya, kehadiran ‘kutu buku’di lingkungan pendidikan cenderung mendapat kesan yang tidak menyenangkan. Faktor paling sederhana dari asumsi ini adalah istilah ‘kutu’ yang disandingkan dengan ‘buku’. Istilah ini notabene memuat konotasi yang kurang mengenakkan. Kutu adalah mahluk kecil pengganggu yang gaweannya adalah menjadi parasit. Padahal sebenarnya, kutu buku –jika ngotot mempertahankan istilah ini- jauh dari hal-hal tersebuut. Entah karena alasan rima atau hal lain, namun frase ini agaknya cukup sukses untuk memposisikan pecinta buku sebagai orang yang kuper, culun, dan tidak gaul. Sehingga terkadang, tidak banyak kutu buku yang mendapatkan lingkungan kondusif dengan nuansa intelektual yang mendorongnya untuk –paling tidak – mempertahankan statusnya sebagai kutu buku.
Ironi dalam dunia mahasiswa yang juga cukup memprihatinkan adalah adanya budaya copy paste atau asal tempel, baik dari situs internet maupun dari bahan pustaka. Akibatnya, tujuan luhur kurikulum dan atau dosen untuk mendongkrak daya baca dan produktivitas mahasiswa kemudian terbengkalai dengan penyalahgunaan bahan pustaka yang –mungkin bisa dikatakan- cukup melimpah. Bermodal beberapa buku yang setema dengan judul yang berbeda, kita seringkali mencomot beberapa hal yang disampaikan pengarang, lalu print, dan setor. Tidak ada satupun sumbangan pemikiran yang dipaparkan dalam tulisan yang diatasnamakan kita di halaman sampul. Ya, semacam praktik plagiasi level rendah yang lebih tersembunyi dan karenanya lebih aman dan terhormat.
Saya termasuk orang yang kurang suka berlama-lama dengan buku, kecuali saat saya harus mengandalkan buku yang super duper setia untuk kepentingan lembur SKS tugas yang akan ditumpuk esok paginya. Karena itulah saya bersyukur, masih ada orang yang mau memotivasi saya untuk terus menulis dan membaca meski harus lewat cara yang terkadang kurang menyenangkan. Ya, mereka adalah Bapak/Ibu dosen yang tekun memberikan saya tugas menulis makalah dan atau portofolio. Saya sering membayangkan, betapa bekunya otak saya tanpa tuntutan yang kadang tidak mau berkmpromi dengan kelelahan dan kemalasan saya tersebut. Sampai saat ini, saya tidak bisa menjalani tugas makalah dengan senang dan ikhlas hati, namun saya merasakan kepuasan tak terhingga saat menyudahi sebuah tulisan. Membanggakan diri bahwa meski saya jauh dari buku, saya ternyata masih bisa mengeksploitasinya..
Saya seringkali tidak habis pikir membayangkan seorang kutu buku. Saya ingin tahu, dunia apakah yang ditemukannya dalam barisan bacaan dan kerutan dahi atau bahkan penglihatan yang kemudian terganggu dan kacamata yang semakin tebal? Apakah yang menenggelamkannya sehingga ia betah dan seolah enggan berpindah? (Ada yang mau membantu saya?)
Ironi lain yang bagi saya cukup menjadi sebuah paradoksa yang mencengangkan adalah daya beli kita yang secara umum –bisa dikatakan- menurun untuk anggaran bahan pustaka. Bandingkan saja berapa jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk keperluan pulsa dengan anggaran untuk membeli buku. Buku tidak lagi menjadi kebutuhan primer mahasiswa namun menurun derajatnya menjadi kebutuhan yang tidak diperhitungkan. Tidak heran jika saat ini kita masih hanya bisa menjadi pembaca, namun belum bisa mengukir sejarah dengan membidani lahiranya sebuah buku.
Fortunately, kita masih saved by the condition, dengan perpustakaan yang cukup memadai serta budaya pinjam buku ke teman. Selain itu, keberadaan internet yang menawarkan pengetahuan instan cukup menyelamatkan kita dengan memberikan akses ilmu pengetahuan. Namun lagi-lagi, seperti halnya buku, internet pun akan menjadi senjata makan tuan jika tidak disikapi dengan arif. Hal yang paling tampak ke permukaan dari dua medium ini, seperti yang saya disinggung di atas, adalah buadaya copy paste. And the result of this, kita bukannya dibikin pintar dan dinamis oleh fasilitas-fasilitas tersebut, namun kehadirannya malah menjadi medium pembodohan dan kelesuan berpikir.
Pada akhirnya, sejauh apapun saya dari buku, saya cukup menyadari bahwa buku adalah sahabat paling setia yang tidak akan pernah marah meski seringkali diacuhkan dan tidak dianggap. So, what`s next? Bagaimana dengan Anda? Ya, apa yang saya tulis pada akhirnya adalah refleksi pribadi yang sifatnya juga sangat subjektif. Semoga Anda tidak menyesal membaca tulisan ini. Terakhir dan mungkin yang tidak kalah penting, ada baiknya kita merenungkan kembali kata-kata Joseph Alexandrovitch Brodsky, bahwa, ada kejahatan yang lebih buruk dari membakar buku, salah satunya ialah tidak membaca buku.
visit my blog at www.serumpunkataselumbungcerita.blogspot.com
[i] Lih. Musaheri, “Membaca Tiang Peradaban”, dalam Jurnal EDUKASI, hlm. 22 atau baca dalam Yudi Latif, “Memuliakan Kembali Pikiran”, di Harian Kompas, 2005