Ketika masih di Jakarta untuk suatu keperluan beberapa pekan yang lalu, aku mendengar kabar dari televisi maupun situs-situs di internet bahwa Merapi meletus. Tak berada di Jogja seperti biasanya, aku kurang begitu merasakan suasana letusan itu. Selain karena kosku cukup jauh dengan pusat bencana, aku belum pernah mengalami bencana yang bisa dibilang real disaster. Selama ini, paling mentog, aku hanya merasakan nyaliku berdetak satu-satu saat ada gempa kecil yang sekadar lewat atau sesekali pernah bertemu dengan putting beliung. Selain itu, buat aku, Jogja masihlah kota hunian yang menjanjikan. Meski banyak yang mengatakan bahwa Jogja hari ini tak seramah dulu, aku jauh lebih menyukai Jogja dibanding Surabaya, Semarang, apalagi Jakarta. Buat aku, Jogja adalah kota kecil yang masih lekat dengan nunansa ke’desa’annya.
Sebab itulah saat pertama kali mendengar bencana letusan Merapi di Jogja, aku serasa percaya tak percaya. Miris rasanya harus membayangkan kotaku akan dirundung duka. Tapi itulah yang aku liat di layar tivi maupun di situs-situs internet. Nama ‘CANGKRINGAN’ pun disebut-sebut sebagai kecamatan yang mengalami kerusakan cukup parah. Aku segera teringat bahwa beberapa hari sebelumnya, aku sempat mampir ke Cangkringan bersama temen-temen GM dalam rangka menghadiri acara PKD salah satu fakultas. Meski belum terlalu dekat dengan Merapi, tapi aku cukup merasa bahwa tempat yang saat itu aku pijaki saat ini tengah berada dalam zona bahaya.
Dan, satu hal pun berkelebart di pikirku. Beberapa hari lagi (aku lupa tanggal pastinya), aku dan teman-teman akan menghelat acara tahunan di wilayah Turi yang otomatis juga dekat—bahkan jauh lebih dekat dibanding Cangkringan—dengan Merapi. Aku tak tau bagaimana nasib dan keberlanjutan acara tersebut. Yang pasti sebelumnya, aku sudah menunggu-nunggu kapan momen itu akan tiba. Suasan Turi dan segala kekhasannya membuatku melempar ingatan pada Novemvber 2008 saat acara yang sama. Aku ingin mengulang suasana itu meski di tempat dan orang-orang yang berbeda, namun ternyata keinginan itu belum sejalan dengan kehendak Tuhan.
Lewat chating di salah satu situs jejaring sosial, seorang teman memberitahuku bahwa acara itu akan dipindah mendadak ke bagian selatan Jogja, yakni wilayah Bantul. Ya kecewa juga, pasalnya aku uda excited banged dan udah sedari dulu mengatur jadwal aku bisa stand-by di lokasi meski tidak 24 jam dalam sehari. Namun langkah memindahkan lokasi acara memang satu-satunya pilihan yang ada. Aku mungkin hanya kecewa, perasaan yang jauh amat sangat ringan dibanding temen-temen panitia dan fasilitator yang mungkin harus banyak memforsir pikiran, tenaga, serta uang. Well, setelah mendapat berita itu serta berita-berita lain di televisi, aku sadar bahwa Jogja bener-bener tengah mengkhawatirkan.
Sore, 26 Oktober, kalo ga salah, Merapi memuntahkan letusan yang cukup besar dan memakan korban jiwa maupun material. Salah satu korban jiwa yang nyawanya tidak dapat diselamatkan adalah Mbah Marijan, juru kunci atau sahibul bait Merapi. Sosok Mbah Marijan mulai dikenal sejak peristiwa letusan Merapi yang ga gitu besar pas 2006 kemarin, ketika aku belum di Jogja. Aku belum pernah bertemu dengan Mbah Marijan dan aku hanya mengenalnya melalui cerita dan catatan-catatan tentangnya. Sebab itulah aku tak banyak tau tentang sosok yang bersahaja ini.. Sebatas yang aku liat, Mbah Marijan adalah representasi dari generasi tua yang berpikir sederhana dan fokus. Fokus pada tugasnya dan filosofi hidupnya untuk’ menjaga’ Merapi dan menjadi dirinya sendiri. Simpel dan ga terlalu muluk plus ga kebanyakan request ma Tuhan. Hal itulah yang barangkali terlihat dari momen-momen ia menjemput maut di rumahnya—yang diberitakan meninggal dalam keadaan sujud ketika tengah shalat—ashar.
Terlepas dari benar-tidaknya serta besar-kecilnya kemungkinan adanya rekayasa dalam pembritaan tadi, aku menilai Mbah Marijan sebagai salah satu dari segelintir orang yang spirit hidupnya perlu dilestarikan. Simpel, sederhana, namun fokus pada apa yang menjadi spirit hidupnya. Sayang memang, sepanjang pengetahuanku, Mbah belum sempat melakukan kaderisasi pada calon penggantinya yang akan menjaga Merapi. Tapi dari itu semua, seperti kata pepatah arab, lisanul hal afshah min lisan al maqal. Perilaku dan tindak-tanduk Mbah Marijan sejauh ini—sepantasnya dan sebenere—menjadi teknik kaderisasi yang cukup baik. Masalane kemudian, bagaimana dengan kader-kader yang akan melanjutkan tugas mulia tersebut. Semoga, spirit Mbah Marijan masih akan hidup di tengah-tengah anak cucunya yang akan menjaga Jogja dan Merapi.
Selama tiga tahunan lebih di Jogja, aku sedkit banyak mengerti geografis Jogja. Jogja adalah Daerah Istimewa yang cukup mungil namun apik dengan empat kabupaten, yakni Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunung Kidul. Ada tiga hal yang mungkin menjadi ikon yang cukup identik dengan Jogja, yakni Parang Tritis (Laut Selatan tempat Bunda Nyai Roro Kidul), gunung Merapi, dan tugu. Dosenku pernah bilang bahwa ada paradigma mistis yang mengatakan, jika bisa ditarik garis lurus, maka ada garis linear antara tugu Jogja, gunung Merapi, dan Parang Tritis. So, Jogja ada di antara dua kutub, yakni kutub Selatan, Parang Tritis di Bantul, dan kutub utara yakni Merapi di Sleman. Kemarin, saat gempa Jogja, daerah Selatan mengalami kerusakan cukup parah. Dan hari ini, saat Merapi meletus, daerah Utara Jogja serta kabupaten lain yang berbatasan dengan Jogja (seperti Magelang dan Boyolali) harus sejenak menjadi kota mati.
Jadi, dari perhitungan sederhana semacam itu, malam itu, ketika hujan Pasir sampai di tempatku, aku berinisiatif untuk mencari suaka dan perlindungan (baca: pengunsian) ke arah selatan, Bantul atau Wonosari. Saat aku menghubungi seorang temen via telepon, dia mengatakan bahwa Wonosari menjadi final destination dari masyarakat yang harus dievakuasi. Saat itu, uda lewat tengah malam, aku sudah sampai di Jalan Wonosari, namun aku mengurungkan niat untuk terus naik karena medan yang cukup berat tidak akan mau berkompromi dengan mataku yang cukup mengantuk dan aku yang kelelahan, meski sehabis bangun tidur. Malam—atau dini hari dan pagi itu—menjadi momoen yang cukup menegangkan buat aku, barangkali karena momen pertama.
5 November waktu itu. Aku inget banget, tidurku lelap banget dan banget lelap, sebab seharian aku kecapean mempersiapkan makalah yang harus aku presentasikan besok di kelas Filsafat Bahasa. Ga tau jam berapa pastinya, temen kamarku membangunkanku dan langsung berucap banyak hal. Di luar, suasana sudah ramai. Temen-temen kos pada bangun dan semuanya merengsek ke depan televisi untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Aku masih males beranjak dari tempat tidur dan segera mencari hape yang biasanya jadi barang terakhir yang aku liat sebelum aku memutuskan untuk terlelap. Ada banyak panggilan dan beberapa sms yang intinya sama, menyuruhku untuk bangun dan mengabari bahwa kotaku tengah dilanda hujan pasir, setelah Merapi kembali meletus. Aku bener-bener panik dan kantuk lelahku hilang seketika.
Aku langsung menghubungi beberapa nomor di hapeku. Ksatria, Bapak dan Umik, Mbk Rom, serta Unyil. Minimal, orang-orang itulah yang barangkali paling banyak menyita waktu dan tempatku belakangan ini. So, aku langsung mengabari dan mengontak mereka. Dial pertama, ksatria. Dia sudah terjaga dan menyadari bahwa hujan pasir juga tengah mengguyur genting-genting kamar kecilnya. Mbak Rom, Bapakku, dan Unyil masih terlelap. Panggilan teleponku lah yang membangunkan mereka. Aku bicara seperlunya dan tetap berusaha mengkondisikan diri setenang mungkin di keadaan yang cukup genting itu. (Saat itu aku masih sempat berpikir bahwa ada satu nomor yang seharusnya juga aku dial, sekadar memberitau suara di sana bahwa aku tengah berada dalam keadaan aga genting. Tapi, aku memang wajib mengurungkan niat itu dan menganggap pikiran itu tidak pernah muncul. Bukan waktu yang tepat untuk bermain dengan perasaan)
Setelah mengumpulkan sukma dan kesadaran, aku bergegas ke depan tivi untuk bergabung dengan temen-temen kos. Di sana, sudah cukup banyak teman yang tampak terjaga sedari tadi. Pemberitaan di televisi, selain informatif, ternyata juga mengandung unsur lebay. Entah, apakah unsur ini memang harus ada dalam sebuah pemberitaan demi alasan pasar, yang pasti aku merasa pemberitaan dini hari itu cukup berlebihan. Apalgi jika konsumen berita itu adlah orang tua yang anaknya kuliah/skolah di Jogja. Bisa dibayangkan bagamana panik dan hebohnya.
Terkait dengan sisi lebay media itu, aku punya berbagai cerita dari penuturan temen-temenku. Yang pertama, dari salah satu temen yang menuturkan bahwa orangtuanya rela mengeluarkan kocek setengah juta lebih untuk membayar taksi yang membawa ketiga anaknya pulang dari Jogja menuju Banjarnegara. Yang kedua, seorang temenku yang lain memutuskan untuk mudik setelah ada pengumuman libur dari kampus. Ketika nyampai rumah, sang ibu menyambut temenku dengan penuh perasaan dan keharuan, hingga temenku tersebut membahasakan dengan “seperti menjemput orang dateng berhaji dari Mekkah” plus pake acara memeluk sambil menangis. Dan yang ketiga, cerita lain, seorang ibu yang tiga anaknya sama-sama belajar di Jogjakarta, dijauhkan dari televisi dan siara berita agar tidak berlebihan mengkhawatirkan keberadaan anaknya.
Semua ekspresi itu, memang murni berangkat dari rasa sayang dan kekahawatiran orang tua (terutama orang tua perempuan) terhadap anak-anaknya. Tapi yaaaa..mereka yang tidak tinggal di Jogja dan melihat pemberitaan yang tampak demikian heboh dan darurat, bisa dipasatikan akan berekspresi demikian. Wajarlah, adanya. Dalam menghadapi situasi yang cukup dilematis ini, langkah teraman yang aku ambil adalah dengan meyakinkan orang tuaku (bapak dan terutama umik) bahwa keadaanku di sini tidaklah segaswat seperti keadaan yang diberitakan di televisi. Aku juga berkali-kali mengatakan bahwaaa…tempat aku kos maupun tempat aku kuliah berada adalam radius yang amat banget jauh dengan lokaso bencana. Banyak lah, yang aku ucapkan berkali-kali kepada orangtuaku untuk meminimalisir kekhawatiran beliau-beliau. Well, above all, aku sudah cukup tua dan tanggap bencana untuk menyelamatkan diri sebisa mungkin. So, beliau tidak perlu mengkahawatirkanku terlalu berlebihan.
Selain orang tuaku, beberapa keluarga dan teman dekat juga selalu mengupdate suasana di Jogja, khususnya keadaanku sendiri. Meski kadang males mengangkat telepon dan membalas sms yang cukup banyak itu, aku merasa senang juga diperhatikan orang-orang yang aku sayangi dan pernah seruang dan sewaktu denganku, dahulu, di berbagai tempat dan berbagai alasan. Hehehehe. Karena paradigma ini pulalah, aku kadang protes pada temen dekat yang tidak menanyakan kabarku dengan sms yang sok manja banget, “Kau tak mengkhawatirkanku?” Heheheh..Pede banget emang, tapi aku hanya ingin mencari suasana lain di balik kondisi gempa yang cukup meresahkan dan melelahkan ini. Setidaknya, dari suasana ini juga, aku bisa tau mana temen-temenku yang memiliki rasa sayang dan peduli dengan ekspresi kekhawatiran, sindrom yang barangkali juga menjangkitiku. Hehehe. Jadi, setelah menemukan temen sealiran, aku lebih mudah mengenali gejala ini. Ga nyambung ah. Hahahaha
Selaen hujan pasir, aku juga pernah merasakan hujan air..hehehe..maksudnya hujan abu. Hujan abu ma hujan pasir sebenernya ga jauh beda. Sama-sama mengharuskan warga Jogja untuk mengenakan masker. Hujan abu..pertama kali mengguyur daerah kosku di suatu pagi, sehari setelah aku mendarat di Jogja. Bedane, hujan pasir sedikit lebih menyeramkan dibanding hujan abu. Jika ketika abu, genting kos tak berdecit dan tak menimbulkan suara apa-apa, maka saat hujan pasir datang, serasa ada irama tak beraturan yang menghinggapi atap-atap kos dan membuat penghuninya dua kali lebih resah dan lebih cemas dibanding ketika hujan abu tengah mengguyur. Semoga, hanya hujan abu dan hujan pasir yang sudi menghinggapi kota dan kosku, tidak sampai hujan kerikil apalag nomaden goat (wedhus gembel).
Untuk merapi, meski tak terprediksi, semoga bisa mengerti. Amien.
skip to main |
skip to sidebar

Sekadar nama, yang barangkali akan menjadi momentum banyak hal.. yang ingin kumulai dari entah berapa jauh dari masa ketertinggalanku akan lari dunia yang melebihi kencang hembusan badai...
Welcome to my blog, hope you enjoy reading.
Islamic Calendar
Facebook Badge
Feedjit
IT IS ME!
Labels
TemAn
Copyright 2009
serumpun KATA selumbung CERITA.
Blogger Templates by Deluxe Templates
WP Themes designed by EZwpthemes
Blogger Templates by Deluxe Templates
WP Themes designed by EZwpthemes


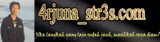
0 comMentz:
Posting Komentar