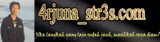Pekan ini adalah examination week. Meski hanya dua MK yang tergolong tidak begitu berat, namun perasaan was-was serta phobia menghadapi episode itu cukup dominan. Apalagi, otakku telah cukup lama dibekukan dari pernak-pernik dunia akademik selama jangka waktu kurang lebih dua pekan. So abis melewati dua ujian MK itu, aku serasa bisa bernafas sejenak. Meski ntar pekan depan harus terengah-engah lagi. But whataver lah, yang penting enjoyin ajah dulu. Dan idealnya, weekend pekan ini harus menjadi momen yang supportif untuk kondisi belajar yang mengenakkan pekan depan.
Dan karena ujian MK kedua uda kelar pas hari Kamis (kemarin), it means bahwa akhir pekanku dimajukan beberapa hari. Hehehe. Jadwal sudah terscejul untuk akhir pekan ini..heng ot di tempat Unyil plus beberapa kegiatan yang mungkin unplanned. Paling mentok yang ngurusi cucian, setrikaan, nyelesein bacaan buku, dan yang terakhir dan paling mbikin males adalah BELAJAR untuk UJIAN PEKAN DEPAN!! Wohohohoho…Sudah terbayang suasana pojok kamar yang -tidak mengenakkan, konsentrasi yang buyar dan aku pugar lagi, nyamuk-nyamuk nakal, dinding-dinding kamar, alunan lagu, dan diktat serta bahan kuliah.
Berenang-renang dahulu aja. Kamis sore (25/11) aku masih harus mengurusi beberapa hal—yang hingga saat ini belum semuanya rampung—sebelum pada akhirnya bisa berangkat ke tempat Unyil. Pas di bangjo sebelah kampus, hape di saku celanaku bergetar. Aga lama, berarti panggilan bukan sms. Konsentrasiku riding mulai buyar, antara melihat layar hape atau tetep diem menunggu lampu hijau. DECIDE NOW OR NEVER, pikirku. Keputusannya adalah tetep diem dengan dua tangan di stang tanpa ada yang merogoh hape ke saku celana. Tak lama lampu hijau menyala. Kali ini keputusanku tepat. Hampir tak ada suspense di sepanjang jalan. As like usual. Satu-satunya pemandangan yang menarik pikiranku malam itu hanyalah karena ada obral baju bekas artis di depan easy dining Jl. ADisucipto yang dikerumuni oleh banyak orang. Lucu kupikir. Otak analisis nakalku bekerja. Mempertanyakan banyak hal yang sama sekali lucu dan kedengerannya tak penting. Tapi percaya atau tidak, hal itu adalah aktivitas yang paling sering kulakukan saat tengah seorang diri mengendara. Menikmati jalan, membaca semua tulisan sebisa mataku, dan menggelar monolog-monolog pribadi. Ujung-ujungnya satu, AKU KETAWA DALAM HATI. Hahahah
Sampai di rumah Unyil, Mb Dhian (mba’e Unyil yang pertama) membukakan pintu. Selaen kos Mb Rom, rumah Unyil ini adalah tempat escape dari kos yang paling sering aku kunjungi. Hehehe. Ada lah, alasan dan keperluan untuk bertandang ke tempat ini. Mulai dari urusan akademik, akomodasi, logistik, hingga urusan lain-lain. Di rumah itu, Unyil tinggal bareng kedua mbaknya yang masih sama-sama kuliah. So, moment yang paling sering memaksaku untuk nginep di tempat ini adalah ketika Unyil sendirian saat mbak-mbaknya sedang bepergian atau tourin ke manaaa gitu. Dan untuk malam itu, alasanku nginep tempat itu adalaaah..karena di kos banyak amat nyamuk nakal, ada janji ma Mb Dhie, sekaligus mau week-end-an. Entah apa agenda spesifiknya. Yang jelas judul besarnya demikian. Selanjutnya ya let it flow. Hehehehe.
Tak seperti Unyil dan Mb Intan (mb kedua Unyil), Mb Dhian terlihat sudah ready alias siap dengan performa dan busana orang yang akan keluar rumah. Aku tak tau akan ke mana. Namun beberapa detik kemudian, Mb Dhian memberiku sebuah tawaran yang cukup dilematis. Hehehehe. What’s that? NONTON HARRY POTTER DI AMPLAS,. Angel dan Demon pun beraksi. Hehehe. Aku ga bisa menentukan mana yang Angel dan mana yang Demon (iki kontaminasi karena aku lagi mati-matian memenej rasa penasaran dan rasa tak ingin beranjak dari novel Dan Brown). Intine, aku punya alasan untuk menerima dan aku juga punya alasan untuk menolak. Aku berpikir sejenak, sementara virus yang ingin mengkontaminasi di sekelilingku bertebaran tanpa filter. Yang ada di pikiranku adalah beberapa variabel-variabel besar berikut;financial, Harry Potter mania, taste a new flavor (mencicipi pengalaman baru maksudnyaaaaa..), weekend, refreshing, dan setelah dikalkulasi, total sumnya adalah..APOLOGI LEBIH BESAR DIBANDING ANOMALI. Lagi-lagi aku dak bisa menentukan mana yang apologi dan mana yang anomali. Intine, berbekal beberapa perhitungan, akhire I DECIDE!! Oke, aku meluuuuuuuuuuuuw,,,
Tak perlu banyak waktu untuk bersiap-siap. Beberapa menit setelah mengiyakan ajakan itu, aku sudah duduk manis di motor dengan driver mb Intan. Di depanku, Unyil bonceng ma Mb Dhian. Sebagai dua orang termuda di antara rombongan itu, aku dan Unyil bersikeras tak mau jadi driver. Hehehe. Ada enak dan enaknya juga menjadi pembonceng. Namun dalam hal ini, aku biasanya hanya meng-list orang-orang yang good at driving dan bisa membuatku nyaman berada di belakangnya. Heheheh. Males mau berteori lebih serius dalam hal ini.
And to be known and to be remained, exactly by me myself, malam itu adalah malam pertama aku akan menonton film di bioskop. Hohohohohoho. Selama ini aku pikir, nonton film di bioskop dan di laptop tak jauh berbeda. Sensasinya tetap dapet, dan tentunya—ini yang selalu menjadi alasan terkuatku—nonton di kos akan jauh lebih mendukung gerakan irit bulanan yang selalu aku lakukan. Hehehehe. Tapi dasar aku lagi tergoda dan ingin mencicipi pengalaman baru, akhire malam itu, keputusan untuk ikut nonton aku ratifikasi. I JUST WANNA KNOW. Itu alasanku. Bisa jadi ini adalah moment pertama dan terakhir. But surely, biarkan akhir cerita tulisan ini yang akan menjawabnya.
Selama ini, keengananku untuk mencoba hal-hal baru yang belum pernah aku lakukan sebelumnya lebih banyak disebabkan karena AKU DAK MAU OON-OON SENDIRI, apalagi bersama dengan orang yang juga tidak memiliki pengalaman an-sich seperti aku, dalam suatu hal tertentu. Sebab itulah, untuk berani masuk ke suatu tempat yang belum pernah aku kunjungi sebelumnya, aku kerap kali baru mau mengangguk jika bersama dengan orang yang uda pernah mengunjungi tempat tersebut. Terdengar klise memang dan cukup menggugurkan karakterku sebagai orang yang menyukai tantangan. Namun itulah apa adanya. Jadi, ketika ada ajakan Unyil and sisters, implus untuk ngangguk jauh lebih kuat dibanding implus untuk menggeleng. Minimal, bisa tau dikit tentang banyak hal.
Ok, next venue adalah di loket pemesanan karcis nonton. Seperti yang pernah aku bayangkan sebelumnya, loket itu terdesain mirip dengan pemesanan tiket-tiket lain. Suasana pun tak jauh beda. Ada negosiasi, transaksi, lalu basa-basi. Mb Dhian sebagai ketua rombongan dan orang tertua—terdewasa—di antara kami segera menghandle urusan itu. Aku memerhatikannya meski tak seksama. Berharap jika suatu saat ada yang mengajakku ke loket macam itu, aku sudah bisa tau apa yang harus aku lakukan. Hehehe. Antisipatif buanget sich. Mb Dhian sibuk berbicara dengan si petugas dan akhirnya vonis pertama malam itu yang aku terima adalah..KAMI BEREMPAT MASIH BISA NONTON JAM SETENGAH SEPULUH DENGAN MENDAPATKAN KURSI VVIP. And you know what, kursi VVIP itu adalah kursi paling depan. Kursi di deretan belakang dan tengah sudah pada diboking dan sebagai pendatang terakhir di loket itu, kami berempat mendapat tempat duduk VIP. Aku no koment ajah dan belum bisa membayangkan, seberapa dekat ataupun seberapa jauh jarak antar aku dan layar. Yang ada di pikiranku adalah, malam itu aku akan mencicipi pengalaman baru. Dewas enough..
Kami berangkat dari rumah Unyil sebelum Isya’ so kami masih harus menghabiskan waktu beberapa lama di Plaza tergede se-Jogja itu sebelum bisa masuk ke bioskop. Dan satu hal lagi yang belum terlakoni. MAKAN MALAM. Perutku keroncongan bahkan lebih berisik daripada suasana di plaza itu. Dan hal teraman yang bisa aku lakukan adalah diam dan tak banyak komentar. Lebih fokus pada kelaparanku dan rundown-rundown di mana dan kapan aku bisa makan. Kami berempat pun menyisir beberapa penjuru Amplas hendak keluar mencari makan outdoor—di luar Amplas dan di luar pajak yang guede banget—dengan segera menemukan pintu keluar samping jalan gede.
Namun rundown ya tinggal rundown. Di luar, paku-paku air hujan tampak masih lebat menyerang aspal, bumi, pepohonan, atap-atap rumah dan kendaraan, serta semua isi bumi. Tak terasa deras bagi orang yang berteduh di bawah atap namun akan terasa amat banget lebat bagi mereka yang terpaksa menghadapi hujan dengan hanya mengandalkan atap bernama langit. Apalagi sambil berjalan dan atau mengemudi. Nuansa terasa lebih sense touching dan lebih menggigit. Duduk-duduk di tangga depan Amplas menunggu hujan mau reda hanya menambah suasana kelaparan dan kerinduan pada makanan. Aku mencoba mencairkan keadaan dengan ngutek-ngutek hapeku. Smsan dan fb-an yang sebenarnya tidak terlalu penting dan hanya diniatkan untuk mengisi waktu. Namun hujan belum juga reda, persis eperti rasa laparku (dan mungkin ketiga orang disampingku). Akhirnya, tak ada pilihan lain keculai menyisir penjuru Amplas degan satu tujuan; mencari makanan dengan harga minimalis.
Mencari makanan yang bisa mengenyangkan—minimal hingga besok pagi—di bawah harga sepuluh ribu agaknya merupakan suatu kesalahan sejarah. Ga mungkin nemu. Kalo di angkringan dan di burjo mungkin uda full tank, lha iki nang Amplas. Pilihan pertama adalah KFC, sebab referensi menunjukkan bahwa tak ada stand McD di Amplas. Mengapa pilihan jatuh ke perusahaan makanan milik Amerika itu, aku pikir kami berempat lebih memilih makanan yang uda pasti harga, kualitas, dan spesifikasinya. Jadi tak perlu khawatir akan terjadi kesalahan dalam menentukan pilihan setelah makanan tersaji di meja atau ketika akan membayar di kasir. Namun setelah masuk dalam in line alias antrian dan memelototi harga-harga yang tertera, kami akhirnya sepakat untuk mencari tempat lain yang barangkali lebih representatif (bisa diartikan, makanan lebih bergizi, lebih murah, dan tempat juga lebih enak. Hehehe. Ngeles). Okelah, akhirnya kembali walking-walking looking-looking.
Well, setelah celingak-celinguk sok kul, akhirnya dengan kesepakatan emosional dan kultural kami menetapkan pilihan dengan setengah hati ketika melihat sebuah stand tempat maka yang berbrand..mmm..aku lupa. Intine ada kata-kata Jakarta gitu. Seperti biasa, konsumen duduk di tempat yang disediakan lalu tugas selanjutnya adalah, menentukan pilihan yang akan disantap. Aku tak bisa memastikan apa yang ada di pikiran tiga saudara yang ada di sebelahku. Hanya, dalam hal ini, aku mulai merasa bahwa nafsu makanku beranjak berkurang ketika melihat daftar harga di lembaran menu itu. Whahahah..Tidak terlalu mahal jane, namun ada pikiran lain yang membuat nyaliku cukup menciut. Aku kawatir makanan yang aku beli dengan harga melambung itu tersaji dalam kualitas dan kuantitas yang tidak sepadan. Maksudnya tidak bercitarasa dan tidak bisa mengenyangkan. Hehehe. Dalam beberapa hal, manusia memang kepastian. Termasuk dalam moment malam itu. Mb Intan pas itu sudah menentukan pilihan pada semangkuk mie ayam. Namun akhirnya, setelah lama memelototi list menu dan tak juga mendapatkan pilihan yang representatif, pilihan teraman dan terkonyol pun mulai terpikir…CANCEL dan menuju PINTU EXUT!!
Ternyata tidak hanya aku yang merasakan keraguan epistemologi kala itu. Hehehe, ga nyambung. Barangkali memang benar kata pepatah, jika nuranimu tak merestui, urungkanlah langkah. Aku juga membacanya dari tiga wajah di sampingku, meskipun toh Mb Intan uda menetapkan pilihan. Akhirnya, setelah menimbang, mengingat, kami pun memutuskan untuk meng-cancel makan di tempat itu. Pola komunikasi yang dipilih pun sangat jentel, jujur namun disampaikan dengan cara yang halus dan tidak menyakitkan. Untungnya pas itu aku tidak kebagian duty untuk menghampiri si pelayan dan menyampaikan maksud untuk meng-cancel, Mb Dhian lah yang melakukan misi itu. Dan akhirnya berhasil. Kami berempat keluar dari tempat itu dengan perasaan suka cita tanpa ada yang tersakiti. Ya nda ya? Au ah..
Yang namanya pilihan yang uda ditetepkan Tuhan, bagaimanapun dia lepas, akhirnya pasti akan dihampiri lagi. Teori ini biasanya digunakan dalam terminologi jodoh, namun malam itu aku juga melihatnya dari alur cerita selanjutnya. Kami akhirnya duduk dan makan malam di KFC, di tempat yang sebelumnya kami tinggalkan. Mungkin hujan memang menjadi penghalang untuk tidak mencari makanan outdoor, namun pada saat yang sama, hujan juga menjadi alasan untuk akhirnya nangkring di tempat yang pernah ditampik sebelumnya tersebut. Jika digeneralisasi, maka teori ini bisa banyak ditemukan dalam alur kehidupan manusia. Suatu hal yang dianggap hambatan atao gangguan dan kerap bikin gerah tak jarang sekaligus bisa menjadi alasan untuk kelahiran suatu hal yang lebih indah. Ya, karena skenario Tuhan emang gabisa dihack.
Ok, back to the story. Di KFC, suasana berjalan seperti biasa. Aku hanya sempat berpikir sedikit hal. Bangsaku terjajah di negaranya sendiri. Penduduk pribumi—termasuk aku, tentunya—lebih bangga dan suka mengonsumsi apapun yang bisa meningkatkan gengsi mereka, hal-hal yang ternyata didominasi oleh produk dan atau perusahaan asing. Jane, hal yang menyebabkan keadaan tesebut terjadi ku karena produk dalam negeri emang kurang berkualitas—dibanding produk manca—atau memang karena penduduknya lebih merasa nyaman dan gaya jika mengonsumsi produk dari luar? Wallahu a’lam lah, aku juga tak tau harus memberi jawaban bagaimana. Agaknya aku belum menemukan jawaban yang representatif. Aku seharusnya tak sempat berpikir banyak di tengah rasa lapar yang uda akut itu. Namun, karena aku terjebak dalam antrian yang cukup panjang, mau tak mau ada wacana yang muncul di otakku dan aku hanya mengutak-atiknya dikit. I NEED TO EAT SOON…Hehehehe
Sampai di meja, Unyil dan Mb Dhian yang sudah lama menunggu tampak sudah tak sabar. Kami segera mengambil posisi ternyaman dan segera menghajar mangsa yang tersaji. Makan bersama memang selalu menambah kedekatan emosional yang juga berpengaruh dalam menambah citarasa makanan. Makanan kurang enakpun akan terasa semakin enak jika dimakan bersama, lha ini makanan yang uda enak, masih anget pula. Dimakan bareng dalam keadaan laperrr. Rasanya delicious very quietly dah. Sayang memang, untuk styleku, porsi yang menyuguhkanku lebih banyak lauk dibanding volume nasi adalah porsi yang tidak pas. Namun, rupanya hal terebut uda terlebih dahulu diantisipasi oleh pengusaha fasr-food. Langkah jitunya yakni menyuguhkan minuman bersoda. Jadi, walaupun kerasa dikit dan tidak mengenyangkan, akan tetapi soda cukup berandil dalam memberikan efek kenyang—yang mungkin sesaat—bagi orang yang mengonsumsinya. Ini intrik ekonomi. Hehehe. Pas ngantri tadi, mb intan sempat ngomong kalo sebuah penelitian mengatakan bahwa soda bisa memperlambat loading otak. What?? Bagaimana dengan otakku yang sudah selalu problem loading page? Namun dalam keadaan yang mengharuskanku mengambil satu-satunya pilihan yang ada, aku memang tak bisa berbuat banyak selain menyeruput segelas pepsi yang merupakan jatahku.
Salah satu ritual yang selalu muncul pada saat makan bersama adalah ngobrol. Sejak kecil aku didoktrin bahwa bicara saat makan akan mengundang setan yang akan ngampung makanan yang dikonsumsi. Sehingga, subjek akan merasakan sensasi rasa kenyang yang kurang full. Heheh. Aku tak tau hal tersebut benar adanya, memiliki landasan (bukan landasan pacu), atau hanya mitos yang dikukuhkan dari generasi ke generasi (bukan slogan biskuit Roma). Namun aku sendiri memang melihat ritual itu sebagai hal yang sangat sulit untuk dipisahkan dalam momen makan bersama. Justeru kadang, ritual makan bisa jadi taktik jitu dalam pola komunikasi. Entah, kalopun itu tidak etis, semoga tidak kebangetan. Sebab aku—bisa dipastikan—tidak bisa autis ketika makan.
Dan seperti juga momen-momen makan bersama sebelumnya, di meja kecil dengan empat kursi itu, kami mulai ngobrol-ngobrol ringan hingga akhirnya sebuah insiden terjadi. Mb Dhian pas itu berekspresi dengan gerakan tangannya—saat bercerita sesuatu yang off the record dan tidak etis diceritakan di forum ini—yang dua detik kemudian menyenggol orange juice di depannya hingga alirannya membasahi gamis serta tas mb Dhian. Mb Dhian panik namun masih sempat ketawa-ketiwi sambil mengeluhkan bahwa persediaan tissue di tasnya uda habis. Namun Mb Dhian tak kekurangan akal. Dia melakukan pertolongan pertama dengan cara jitu serta singkat untuk mengeringkan bagian tengah gamisnya yang terkena tumpahan. Dengan bantuan Mb Intan, tujuh menit kemudian, Mb Dhian kembali dengan senyum mengembang dan gamis yang sudah bersih tanpa satupun indikasi bahwa gamis tersebut sebelumnya sempat membentuk peta pulau tak bernama dari tumpahan orange juice.
Tak berapa lama setelah Mb Dhian kembali, kami berempat sudah bergegas meninggalkan meja makan dan segera menemui final destination yang malam itu dibela-belain ampe mati-matian. Kami akhirnya benar-benar menuju final destination setelah meminta tolong seorang pelayan untuk membungkuskan sisa ayam yang masih layak konsumsi. Lagi-lagi untuk hal ini, Mb Dhian sebagai ketua rombongan yang ternyata memiliki pedemeter paling tinggi di antara kami berempatlah yang menghandle urusan ini. Cukup dengan sedikit senyum dan perkataan yang lugas dan sopan, si pelayan langsung membalas dengan perlakuan yang tak kalah ramah. Sip lah. Aku semakin yakin, malam itu, bahwa dari siapapun yang kita kenal, apalagi hingga menjadi teman, ada banyak pelajaran yang bisa dieksplotasi (baca: diambil). Siapapun dia.
Abis gitu, kami berempat masih harus menunggu beberapa saat di area bioskop sebelum pintu venue 4 terbuka dan kami bisa langsung masuk, mendaratkan pantat di seat berharga lima belas ribu dalam durasi kurang dari tiga jam. Namun ternyata penantian menuju jam setengah sepuluh (dari jam9) masih mengharuskan kami berempat menggunaan stock kesabaran sudah menipis. Alhamdulillah dalam keadaan itu, kami masih dapat tempat duduk yang enak, meski tidak berkoloni empat orang. Aku ma Mb Ient dan Unyil ma Mb Dhia. Dengan Mb Ient, aku membincangkan apapun yang bisa diobrolkan. Bincang-bincang santai lah, istilahnya. Sambil sesekali memelototin hape dewe atau hape masing-masing. Aku tak tau apa yang dibincangkan Unyil dengan Mb Dhian. Namun aku tau saat itu, Unyil tengah memikirkan sesuatu yang lagi-lagi off the record. Dalam masa penungguan itu, salah satu temenku menelpon dan aku hanya bisa menemaninya ngobrol tidak berapa lama. Yayaya, sebab some minutes later, aku akan masuk ke ruang pemutaran pilem. UNTUK YANG PERTAMA KALINYA. Hehehehe.
Saat waktu itu akhirnya tiba, aku mengikuti ritme di sekelilingku ajah. Yang ada di bayanganku adalah tiga sosok laki-laki bernama Arai, Ikal, dan Jimbron yang berhasil membobol security di bioskop kampung mereka namun akhirnya ketauan. Dua petugas di depan pintu masuk yang mengecek tiket para penonton sudah tampak lelah dan suntuk. Barangkali jam ini adalah shift terakhir mereka. Entah. Yang pasti aku mulai berpikir seberapa akurat kemanan dalam sistem ruang bioskop, adakah kemungkinan untuk dibobol, dan lain sebagainya. Namun yang paling mendominasi pikiranku saat itu adalah…Kursi empuk seharga lima belas ribu yang tengah menungguku…
And that seems like a dream. Emosiku bener-bener hanyut dan akupun bisa sepenuhnya lepas dari rasa kantuk, lelah, males, dan hal-hal laen yang berpotensi untuk mengurangi asyiknya nuansa malam itu. Aku mulai faham mengapa orang-orang banyak merelakan duitnya untuk nonton ke bioskop. Selain demi alasan gengsi dan uptodate, suasana dan nuansa yang begitu kental di ruang bioskop juga akan meninggalkan kesan mendalam bagi para penonton. Meskipun banyak aturan, bioskop juga memberi ruang kebebasan penonton untuk berekspresi. Ketawa sekeras mungkin, tereak seekspresif mungkin, tegang dengan tensi setinggi mungkin, dan luapan emosi lainnya. Ckckckckc. Aku impresif banget di pengalaman pertama ini. Sedikit banyak juga dipengaruhi oleh film yang ditonton siiiiiiiiiiyyy..Harry Potter yang aku ikuti riwayat hidupnya sejak dia belum dilahirkan. Hahahaha. Lebaaaaaaay..
Nonton Harry Potter, banyak lah, catatan di dalamnya. Dalam setiap edisi, Harry Potter tak pernah lepas dari ketegangan, suspensi, konflik yang tak diduga, alur yang mendadak, penokohan yang kuat, animasi yang keren, serta ending yang kadang..mmm…menggantung. Belum lagi dengan mantera-mantera, nama-nama tokoh, aliran, nama-nama tempat, istilah-istilah baru, dan lain sebagainya. Intine buat mereka yang tak mengikuti HP sedari awal dan atau baru melihat HP di edisi 7 (1)ini, yang ada di kepalanya pastilah kata JAKA SEMBUNG (dengan tensi yang berbeda-beda). Yayaya, salah satunya adalah orang yang duduk di sebalah kiriku..(namanya tak usah disebutkan. Khawatir dia tersungging. Hehehehe. Piiiiiiiiiiiisss..Piiiiiiiiiisss). Dan seperti pada HP 5, kisah asmara dan adegan syur (baca:ciuman) juga menjadi bumbu dalam HP 7 ini. Padahal di kursi sebelahku, sempat kuliat ada adik-adik seumuran adik keduaku yang matanya tampak bahagia akan segera menonton HP 7. Ya embuhlah. Malam ini seharusnya dia obob lelap karena besok harus sekolah. Bukannya nonton HP lagi in the hoy ma Ginny Weasley. Ih, normatif ah. Hahaha.
Duduk di kursi paling depan deket pintu exit, aku cukup mampu melupakan segala hal yang selama ini membeku dan mengendap dalam pikiranku. Ujian, skripsi, masa depan, orang-orang terkasihku, skandal keci hingga skandal besar, termasuk status terbaru yang aku update di hatiku. Hehehe. Wis, I almost forget that at all. Yang ada di mataku mendominasi semua alam pikiran dan perasaanku. Really sense touching lah. Dan seperti biasa, ketika menjalani aktivitas yang disukai, tak ada yang mau peduli pada waktu hingga ketika waktu menunjukkan dirinya dalam wujud yang lain (baca: menunjukkan waktu menonton sudah habis), barulah semuanya tersadar bahwa mereka telah melewatkan waktu yang cukup lama dengan perasaan yang menyenangkan hingga waktu terasa sangat singkat. Yayaya, relativitas tentang itu memang uda aku sadari. Hehehe.
Ketika nama penerjemah teks terjemah Indonesia muncul di layar, itu artinya waktu penonton sudah habis yang juga berarti instruksi untuk segera keluar. Kami berempat, dengan emosi yang uda terkuras, masih menyempatkan ke hammam untuk merepair anything. Jalan keluar cukup melelahkan, karena sempat bingang-bingung milih lantai yang akan jadi destination abis kami turun dari lift lantai tiga, ketika eskalator sudah dinonaktifkan bahkan di-satpam line dengan rantai aga gede. Aku tak banyak komen karena Amplas memang bukan daerah kekuasannku. Heheh, maksude aku jarang banget ngluyur ke tempat ini. Terlalu lux ajah menurutku dan aku pun memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan dengan manajemen parkir di plaza ini. Alhamdulillah setelah berputar-putar (baca: naik-turun lift dan celingak-celinguk), kami akhirnya bisa pulang dengan lelah, kantuk, plus juga suka cita. Uda lewat tengah malam saat itu. Namun dengan rombongan beranggotakan empat orang, sepi menjadi kurang begitu bertaring…
Setelah malam itu, aku merasa ada satu pengetahuan taktis yang aku baru ketahui. Pengetahuan taktis bagaimana dan apa saja prsedur seorang (calon) penonton bisa menikmati sebuah film yang sudah dipilihnya. Namun sesuai teori lama, I know more, I don’t know more. Satu pengetahuan menuntut pada pengetahuan lain. Jika malam itu aku tau cara dan prosedurnya, aku malah penasaran lagi dengan banyak hal. Apa ae lah, mulai dari manajemen bioskop, gaji bulanan karyawan, pola rekrutmen, dan..banyak lain lah, yang intine berdasar satu kaidah. I JUST WANNA KNOW. Belum lagi tentang esensi dari film yang sukses bikin aku sprot jantung dan shocking soda itu. Hmmmmm..Di mana-mana, sisi perasaan yang dieksploitasi oleh produser film atau sinetron adalah RASA PENASARAN. Aku dewe uda tak sabar dan tak kuasa membayangkan, bagaimana Harry dkk akan melanjutkan perjalanan mereka mendapatkan next Horcurx.
Semogaaa…mind refreshing malam itu bisa mendongkrak staminaku menghadapi ujian pekan depan. Puji Tuhan..
*) Untuk Yyh; Jangan mutung karena aku nonton duluan yaaaaaaaaa…Piss, piss…tar bagian 7(2)nya kita nonton bareng dech. Hehehe. Be happy there. Miss yu full tank.
Jumat, 26 November 2010
Senin, 15 November 2010
Deket Boleh Asal Jangan Kedeketan
Entahlah, apakah judul di atas sudah cukup memenuhi kualifikasi EYD ataukah tidak. Intine, secara operasional dan pragmatis, orang yang membaca judul di atas bisa diperkirakan bisa paham dengan apa yang bercokol di kepalaku. Ya, intinya yang ada di benakku adalah, dalam konteks ini, menjalin sebuah hubungan—entah persaudaraan atau pertemenan atau yang sejenis—pada dasarnya adalah hal yang sah-sah saja, natural, manusiwi, dan wajar. Dalam pertemanan itulah, masing-masing orang yang ada di dalamnya bisa saling mengisi dan menadah. Saling memberi dan menerima. Dan dari intensitas itulah timbul semacam..mm…kedekatan batin, ikatan emosional, dan lain sebagainya yang juga banyak dipengaruhi oleh tensi kedekatan fisik.
Dalam skala yang lebih kecil lagi, aku jane terbetik keinginan untuk menulis catatan ini setelah membaca salah satu berita tentang kedatangan si Berry alias presiden AS ke Indonesia beberapa waktu yang lalu. Banyaklah, yang tersisa dari kunjungan itu. Namun yang paling menarik perhatianku adalah kejadian saat Menkominfo bersalaman dengan isteri Obama yang notabene adalah wanita. Hehehehehe. Mengapa aku tertarik, jawabannya adalah karena aku sering merasa berada dalam posisi seperti Tifatul.
Dan seperti biasa, aku tidak tengah menulis catatan yang bernuansa normatif sentris apalagi judgment. Masalah baik-buruk benar-salah, aku lebih suka menyerahkan pada orang lain, katakanlah pembaca atau orang yang pernah mengalami kejadian semacam ini. Terserahlah bagaimana penilaian masing-masing orang, yang jelas penilaian tersebut tidak lahir dari ruang hampa sejarah alias tanpa alasan sama sekali. Tidak mungkin alias impossible.
Aku sendiri, selama ini berusaha sebisa mungkin menghindari kontak kulit dengan lawan jenis. Bukan sok suci atau sok-sok yang laen, aku hanya melihatanya sebagai sebuah prinsip. Prinsip dasar yang prinsipil. Sebab itulah pada awal-awal jadi mahasiswa, aku—hampir bisa dipastika—akan merapatkan tangan jika berada dalam momen menerima uluran tangan ataupun menjadi pihak yang mengulurkan tangan. Dan aku mendapat respon yang bermacam-macam dari cowo-cowo yang berinteraksi denganku. Ada yang ekstrim menolak, ada yang moderat, dan ada juga yang apatis.
Aku sich menanggapinya biasa aja. Buat aku, kontak kulit dengan kesengajaan, selain menurunkan garansi, juga kurang pantas. Minimal buat diriku sendiri. Sehingga, walaupun aku tergolong orang yang cukup suka mensiasati aturan-aturan normatif, dalam hal ini, aku tak mau banyak bertingkah. Norma itu mentog buat aku. Namun setelah dipiki2, ternyata aturan yang aku bilang prinsipil itu hanya berlaku dalam interaksiku dengan temen2. Untuk famili dan kerabat, aku malah keseringan berkotak kulit (baca:salaman) dengan famili laki-laki—baik yang seumuran ataupun lebih tua—yang seharusnya tidak mendapat previlige itu.
Dengan temen-temen pun, kontak kulit—tangan—sulit banget dihindari. Pas lagi kerja di teamwork, lagi dalam suasana genting, keburu-buru, kontak kulit luar biasa sulit dihindari. Sehingga, dengan tingginya intensitas itu, aku merasa vibrasi atau surprising moment ketika bersentuhan tangan dengan cowo semakin menurun. Dulu, aku merasa sangat berdosa besar ketika tak sengaja—apalagi sengaja—berkontak kulit dengan cowo. Yaaaa..Hal tersebut sangat wajar rasanya, dialami olehku yang saat itu masih cukup jarang berinteraksi dengan cowo, meskipun aku punya adik laki-laki. Dan itulah salah satu hal yang dijanjikan waktu. Aku mengamininya. Bener banget…
Masalah jabat tangan itu, sedari awal, aku membuat pengecualian memang. Ada lah—tanpa harus disebutkan di sini—seorang laki-laki yang mendapat priveleg dalam urusan satu ini. Tapi yaaaaaa..Lama-lama, aku merasa perlu melonggarkan pembatasan itu. Awalnya aku dihadapkan pada kebingungan yang cukup membingungkan manakala aku tengah seforum dengan para dosen. Dan ketika acara selese, semua orang di forum itu saling bersalaman. Aku mulai ragu untuk meneguhkan prinsipku kala itu. Akhirnya aku salaman juga. Dengan apologi, berkontak kulit dengan orang-orang hebat bisa memberiku radiasi energi yang menguntungkan bagiku. Entah bisa seefektif apa…
Pada kesempatan yang lain, ketika tengah bertamu ke rumah seorang dosen, rame-rame dengan temen-temen, aku kagok bukan main ketika suami dosenku menjulurkan tangan padaku. Aku langsung menyambut uluran tangannya dan ketika itu aku berpikir satu hal; I’VE BROKE THE RULE I MADE. Karena keseringan dan akhirnya banyak momen yang memaksaku untuk bersikap lain, akhirnya aku membuat pengecualian. Untuk orang yang lebih tua, orang yang dihormati, dan orang yang memilki energi positif yang kira2 bisa ditransmisikan, tak ada salahnya berkontak kulit. Aku pun kemudian berpikir bahwa sintesis dari semua rule itu adalaaaaaahh…Salaman pada seseorang merupakan salah satu simbol bahwa aku respek sama orang itu. Whoever he is
Di lokasi KKN, aku malah lebih sering dipertemukan dengan keadaan yang membuatku tidak enak untuk menjalankan kebiasanku. Kalo pada temen-temen cowo KKN, aku sih tak masalah. Dalam artian, apapun respon mereka terhadap kebiasanku itu, aku tak gitu ambil pusing. Tapi kalo uda berhubungan dengan warga, perangkat desa, dan semua warga berjenis kelamin laki-laki dan aku berada di posisi yang mengharuskanku berkontak kulit, aku merasa bahwa aku tak sama sekali memiliki pilihan lain. Yaaaaaaa…Sebagai seorang pendatang yang ingin belajar bermasyarakart di daerah itu, mutlak bagiku untuk menunjukkan apapun yang bisa membuatku bisa mengekspresikan rasa hormat dan respekku.
Dan, entah ini apologi atau bener-bener terjadi, aku merasakan ada sensasi lain saat bersalaman dengan para warga di lokasi KKN, khususnya Mbah Hadi. Mbah Hadi selalu bisa mengingatkanku pada almarhum kakek yang luar biasa memorable buat aku. Semangatnya, sorot matanya, ceritanya, caranya bertutur, dan segala hal dalam diri Mbah Hadi selalu bisa membuatku bernostalgia dengan sosok kakek. Belum lagi dengan bapak-bapak RT yang luar biasa baik padaku dan temen-temen. Aku merasa mereka sudah setara dengan keluargaku sendiri. Persoalan di sekitar aturan prinsipil itu pun menjadi semakin rumit dan bercabang.
Hmmmm..Belakangan aku memiliki trik jitu dan cerdas terbaru. Heheheh. Berani bersalaman asal pake kaus tangan. Hehehehe. Hal ini sebenarnya juga mempertaruhkan posisi seorang senior di mata kader. He, kedengerennya fantastis banget. Padahal ya biasa ajah. Ya, teknik ini aku temukan saat PKD 2010. Tak enak dan segan rasanya kalo harus merapatkan tangan di depan kader baru yang masih ‘muallaf’ dan perlu direservasi. Tapi ya itu, aku tetep tidak menyukai segala hal yang lebay dan pass the limit, khususnya dalam hal kontak kulit atau kedeketen fisik. Aku langsung mencak-mencak—pada siapapun juga—ketika sudah melampai batas-batas kecangkolangan atau privasi aku, khususnya sebagai perempuan. Entah, dalam hal ini, aku boleh saja dibilang konservatif ato apalah. BUT THAT’S A REAL ME..Semuanya berjalan bukan tanpa alasan…
Sebab itulah ketika publik banyak menyoal perihal Tifatul yang bersalaman dengan isteri Obama, aku merasa ada banyak hal yang patut menjadi refleksiku atas permasalahan spesifik itu. Tidak perlu sebenarnya terlalu mempersoalkan Tifatul yang muslim konservatif, yang berangkat dari PKS, yang Menkominfo, ato bahkan isu mengenai siapa yang terlebih dahulu mengajak bersalaman. Kejadiannya memang demikian adanya. Sulit diteorikan, sebab semuanya terjadi begitu saja. Normativitas fiqh mungkin bisa saja men-judge tindakan Tifatul tersebut sebagai tindakan yang kurang tepat atau tidak seharusnya dilakukan, tapi masalahnya, Tifatul tak hanya memakai kacamata fiqh dalam keadan insidental itu.
Aku tidak ingin membela maupun menyudutkan Tifatul. Aku saat ini hanya berpikir sederhana sebenarnya. Yaaaaaaa…Banyak hal kecil yang dibesar-besarkan secara lebay, sehingga hal besar yang seharusnya mendapat porsi malah terbengkalai. Aku sendiri sering melakukan hal tersebut dan terjebak dalam paradigma yang demikian. Kasus salaman Mega-Hasyim saat mereka berpasangan dalam pemilu juga sempat menjadi diskursus yang cukup menghebohkan. Kala itu, dalam kacamataku yang masih cukup polos dan normatif, hal tersebut murni adalah suatu hal yang tidak pantas dilakukan. Hehehe, sampai muncul istilah menggadaikn (idealisme) agama dengan menjadikannya komoditi politik. Dan hari ini, aku ketawa ngakak mengingat aku pernah punya pikiran seperti itu…
Hehehe. Tapi ya gapapalah, suatu saat, entah itu kapan, bukan tidak mungkin aku akan kembali menertawakan tulisan yang aku tulis saat ini. Begitulah trilogi waktu, proses, dan perubahan. Tidak ada yang abadi selain ketidakabadian itu sendiri. Tidak ada yang ajeg selain ketidakajegan itu sendiri.
Above all, buat aku pribadi, saat ini, dalam keadan dan atmosfir yang demikian, hanya ingin berpikir sederhana dan lurus-lurus saja..DEKET BOLEH ASAL JANGAN KEDEKETAN. Meskipun persahabatan dan kedekatan bisa memangkas batas-batas individualisme, tetap ada batas-batas yang tidak bisa dilanggar dan menjadi harga mati. Jika tak bisa tegas dengan prinsip kecil dari diri sendiri di usia sedini ini, sangat sulit rasanya untuk bisa menghidupkan prinsip yang sudah sulit2 dipilih unutk menjadi prinsip hidup. Jadiii,,,kasian prinsipnya lah, terlanjur dipilih malah ga diladeni. Hehehehe. Dan dalam hal ini, hal yang tidak kalah penting adalah menghargai prinsip orang lain, sebab setiap orang, siapapun dan dalam keadaan apapun, memiliki prinsip. Menjaga dan mengembangkannya adalah tugas mutlak operasional masing-masing person. eheheh
Dalam skala yang lebih kecil lagi, aku jane terbetik keinginan untuk menulis catatan ini setelah membaca salah satu berita tentang kedatangan si Berry alias presiden AS ke Indonesia beberapa waktu yang lalu. Banyaklah, yang tersisa dari kunjungan itu. Namun yang paling menarik perhatianku adalah kejadian saat Menkominfo bersalaman dengan isteri Obama yang notabene adalah wanita. Hehehehehe. Mengapa aku tertarik, jawabannya adalah karena aku sering merasa berada dalam posisi seperti Tifatul.
Dan seperti biasa, aku tidak tengah menulis catatan yang bernuansa normatif sentris apalagi judgment. Masalah baik-buruk benar-salah, aku lebih suka menyerahkan pada orang lain, katakanlah pembaca atau orang yang pernah mengalami kejadian semacam ini. Terserahlah bagaimana penilaian masing-masing orang, yang jelas penilaian tersebut tidak lahir dari ruang hampa sejarah alias tanpa alasan sama sekali. Tidak mungkin alias impossible.
Aku sendiri, selama ini berusaha sebisa mungkin menghindari kontak kulit dengan lawan jenis. Bukan sok suci atau sok-sok yang laen, aku hanya melihatanya sebagai sebuah prinsip. Prinsip dasar yang prinsipil. Sebab itulah pada awal-awal jadi mahasiswa, aku—hampir bisa dipastika—akan merapatkan tangan jika berada dalam momen menerima uluran tangan ataupun menjadi pihak yang mengulurkan tangan. Dan aku mendapat respon yang bermacam-macam dari cowo-cowo yang berinteraksi denganku. Ada yang ekstrim menolak, ada yang moderat, dan ada juga yang apatis.
Aku sich menanggapinya biasa aja. Buat aku, kontak kulit dengan kesengajaan, selain menurunkan garansi, juga kurang pantas. Minimal buat diriku sendiri. Sehingga, walaupun aku tergolong orang yang cukup suka mensiasati aturan-aturan normatif, dalam hal ini, aku tak mau banyak bertingkah. Norma itu mentog buat aku. Namun setelah dipiki2, ternyata aturan yang aku bilang prinsipil itu hanya berlaku dalam interaksiku dengan temen2. Untuk famili dan kerabat, aku malah keseringan berkotak kulit (baca:salaman) dengan famili laki-laki—baik yang seumuran ataupun lebih tua—yang seharusnya tidak mendapat previlige itu.
Dengan temen-temen pun, kontak kulit—tangan—sulit banget dihindari. Pas lagi kerja di teamwork, lagi dalam suasana genting, keburu-buru, kontak kulit luar biasa sulit dihindari. Sehingga, dengan tingginya intensitas itu, aku merasa vibrasi atau surprising moment ketika bersentuhan tangan dengan cowo semakin menurun. Dulu, aku merasa sangat berdosa besar ketika tak sengaja—apalagi sengaja—berkontak kulit dengan cowo. Yaaaa..Hal tersebut sangat wajar rasanya, dialami olehku yang saat itu masih cukup jarang berinteraksi dengan cowo, meskipun aku punya adik laki-laki. Dan itulah salah satu hal yang dijanjikan waktu. Aku mengamininya. Bener banget…
Masalah jabat tangan itu, sedari awal, aku membuat pengecualian memang. Ada lah—tanpa harus disebutkan di sini—seorang laki-laki yang mendapat priveleg dalam urusan satu ini. Tapi yaaaaaa..Lama-lama, aku merasa perlu melonggarkan pembatasan itu. Awalnya aku dihadapkan pada kebingungan yang cukup membingungkan manakala aku tengah seforum dengan para dosen. Dan ketika acara selese, semua orang di forum itu saling bersalaman. Aku mulai ragu untuk meneguhkan prinsipku kala itu. Akhirnya aku salaman juga. Dengan apologi, berkontak kulit dengan orang-orang hebat bisa memberiku radiasi energi yang menguntungkan bagiku. Entah bisa seefektif apa…
Pada kesempatan yang lain, ketika tengah bertamu ke rumah seorang dosen, rame-rame dengan temen-temen, aku kagok bukan main ketika suami dosenku menjulurkan tangan padaku. Aku langsung menyambut uluran tangannya dan ketika itu aku berpikir satu hal; I’VE BROKE THE RULE I MADE. Karena keseringan dan akhirnya banyak momen yang memaksaku untuk bersikap lain, akhirnya aku membuat pengecualian. Untuk orang yang lebih tua, orang yang dihormati, dan orang yang memilki energi positif yang kira2 bisa ditransmisikan, tak ada salahnya berkontak kulit. Aku pun kemudian berpikir bahwa sintesis dari semua rule itu adalaaaaaahh…Salaman pada seseorang merupakan salah satu simbol bahwa aku respek sama orang itu. Whoever he is
Di lokasi KKN, aku malah lebih sering dipertemukan dengan keadaan yang membuatku tidak enak untuk menjalankan kebiasanku. Kalo pada temen-temen cowo KKN, aku sih tak masalah. Dalam artian, apapun respon mereka terhadap kebiasanku itu, aku tak gitu ambil pusing. Tapi kalo uda berhubungan dengan warga, perangkat desa, dan semua warga berjenis kelamin laki-laki dan aku berada di posisi yang mengharuskanku berkontak kulit, aku merasa bahwa aku tak sama sekali memiliki pilihan lain. Yaaaaaaa…Sebagai seorang pendatang yang ingin belajar bermasyarakart di daerah itu, mutlak bagiku untuk menunjukkan apapun yang bisa membuatku bisa mengekspresikan rasa hormat dan respekku.
Dan, entah ini apologi atau bener-bener terjadi, aku merasakan ada sensasi lain saat bersalaman dengan para warga di lokasi KKN, khususnya Mbah Hadi. Mbah Hadi selalu bisa mengingatkanku pada almarhum kakek yang luar biasa memorable buat aku. Semangatnya, sorot matanya, ceritanya, caranya bertutur, dan segala hal dalam diri Mbah Hadi selalu bisa membuatku bernostalgia dengan sosok kakek. Belum lagi dengan bapak-bapak RT yang luar biasa baik padaku dan temen-temen. Aku merasa mereka sudah setara dengan keluargaku sendiri. Persoalan di sekitar aturan prinsipil itu pun menjadi semakin rumit dan bercabang.
Hmmmm..Belakangan aku memiliki trik jitu dan cerdas terbaru. Heheheh. Berani bersalaman asal pake kaus tangan. Hehehehe. Hal ini sebenarnya juga mempertaruhkan posisi seorang senior di mata kader. He, kedengerennya fantastis banget. Padahal ya biasa ajah. Ya, teknik ini aku temukan saat PKD 2010. Tak enak dan segan rasanya kalo harus merapatkan tangan di depan kader baru yang masih ‘muallaf’ dan perlu direservasi. Tapi ya itu, aku tetep tidak menyukai segala hal yang lebay dan pass the limit, khususnya dalam hal kontak kulit atau kedeketen fisik. Aku langsung mencak-mencak—pada siapapun juga—ketika sudah melampai batas-batas kecangkolangan atau privasi aku, khususnya sebagai perempuan. Entah, dalam hal ini, aku boleh saja dibilang konservatif ato apalah. BUT THAT’S A REAL ME..Semuanya berjalan bukan tanpa alasan…
Sebab itulah ketika publik banyak menyoal perihal Tifatul yang bersalaman dengan isteri Obama, aku merasa ada banyak hal yang patut menjadi refleksiku atas permasalahan spesifik itu. Tidak perlu sebenarnya terlalu mempersoalkan Tifatul yang muslim konservatif, yang berangkat dari PKS, yang Menkominfo, ato bahkan isu mengenai siapa yang terlebih dahulu mengajak bersalaman. Kejadiannya memang demikian adanya. Sulit diteorikan, sebab semuanya terjadi begitu saja. Normativitas fiqh mungkin bisa saja men-judge tindakan Tifatul tersebut sebagai tindakan yang kurang tepat atau tidak seharusnya dilakukan, tapi masalahnya, Tifatul tak hanya memakai kacamata fiqh dalam keadan insidental itu.
Aku tidak ingin membela maupun menyudutkan Tifatul. Aku saat ini hanya berpikir sederhana sebenarnya. Yaaaaaaa…Banyak hal kecil yang dibesar-besarkan secara lebay, sehingga hal besar yang seharusnya mendapat porsi malah terbengkalai. Aku sendiri sering melakukan hal tersebut dan terjebak dalam paradigma yang demikian. Kasus salaman Mega-Hasyim saat mereka berpasangan dalam pemilu juga sempat menjadi diskursus yang cukup menghebohkan. Kala itu, dalam kacamataku yang masih cukup polos dan normatif, hal tersebut murni adalah suatu hal yang tidak pantas dilakukan. Hehehe, sampai muncul istilah menggadaikn (idealisme) agama dengan menjadikannya komoditi politik. Dan hari ini, aku ketawa ngakak mengingat aku pernah punya pikiran seperti itu…
Hehehe. Tapi ya gapapalah, suatu saat, entah itu kapan, bukan tidak mungkin aku akan kembali menertawakan tulisan yang aku tulis saat ini. Begitulah trilogi waktu, proses, dan perubahan. Tidak ada yang abadi selain ketidakabadian itu sendiri. Tidak ada yang ajeg selain ketidakajegan itu sendiri.
Above all, buat aku pribadi, saat ini, dalam keadan dan atmosfir yang demikian, hanya ingin berpikir sederhana dan lurus-lurus saja..DEKET BOLEH ASAL JANGAN KEDEKETAN. Meskipun persahabatan dan kedekatan bisa memangkas batas-batas individualisme, tetap ada batas-batas yang tidak bisa dilanggar dan menjadi harga mati. Jika tak bisa tegas dengan prinsip kecil dari diri sendiri di usia sedini ini, sangat sulit rasanya untuk bisa menghidupkan prinsip yang sudah sulit2 dipilih unutk menjadi prinsip hidup. Jadiii,,,kasian prinsipnya lah, terlanjur dipilih malah ga diladeni. Hehehehe. Dan dalam hal ini, hal yang tidak kalah penting adalah menghargai prinsip orang lain, sebab setiap orang, siapapun dan dalam keadaan apapun, memiliki prinsip. Menjaga dan mengembangkannya adalah tugas mutlak operasional masing-masing person. eheheh
Hmhm...
NgoredZ
Rabu, 10 November 2010
Senioritas
Senior sering kufahami sebagai orang yang lebih lama mencecap asam garam kehidupan dalam sebuah komunitas tertentu. Sebagai misal, pas misalnya tengah duduk di bangku kelas I Aliyah, aku bisa menyebut teman-teman yang duduk di kelas II Aliyah sebagai seniorku. Yang pertama, orang tersebut sudah lebih lama mencecap bangku Aliyah dibanding diriku, dan yang kedua, orang yang kumaksud berada dalam satu naungan denganku, yakni, katakanlah dalam hal ini berada dalam sekolah yang sama. Mudahnya, senior adalah kakak angkatan. Ketika masih duduk di bangku sekolah, aku belum begitu akrab dengan kata tersebut dan lebih sering menggunakan bahasa “kakak kelas” untuk merepresentasikan temen yang kelasnya lebih tinggi daripada kelasku.
Sangat mungkin, aku mulai akrab dengan kata tersebut ketika aku mulai masuk dalam dunia kuliah. Ketika bertemu dengan seorang yang belum pernah kutemui sebelumnya, dan katanya pernah sepondok denganku dulu, seorang teman mengatakan padaku bahwa orang tersebut adalah seniorku. Dari momen itu aku mulai menambah satu karakteristik dalam definisi senior, yakni ciri bahwa senioritas tidak harus terlalu terikat dengan kelas formal. Semisal jika ada orang yang pernah sepondok denganku namun ia tak selembaga formal denganku, maka ia juga bisa disebut seniorku, sebab kami pernah minum dari pancuran yang sama. Well, sesudah pertemuan di rektorat baru itu, aku mulai terbiasa dengan istilah senior di telingaku.
Antitesis atau mungkin lebih enak dibahasakan dengan padanan senior adalah junior. Dalam pikiran kecilku dahulu, junior adalah kata untuk merepesentasikan anak kecil. Kesimpulan itu aku dapatkan dari merk sikat gigiku, yakni pepsodent junior. Lama-lama, di lain kesempatan, ketika kakek (ayah ibuku) wafat, ada sebuah celetukan yang membuat aku kembali berpikir. Saat itu, adik tiri ibuku mengatakan bahwa adik cowoku adalah mbah kakung junior, karena face-nya yang aga sama. Dari dua momen itu, aku mulai membangun pemahaman bahwa senior-junior adalah dua padanan kata yang saling melengkapi. Seseorang bisa dikatakan senior jika dia memiliki junior. Ya…begitulah adanya.
Meski begitu, setelah beberapa saat menjalani hari-hari sebagai mahasiswa, aku merasa ada ketidaksetaraan antara intensitas pengucapan senior dan junior, minimal di lingkunganku sendiri. Senior sangat sering diucapkan, oleh orang semua kalangan bahkan. Namun tidak begitu dengan kata junior. Aku kurang terbiasa mendengar kata junior digunakan dalam percakapan di sekelilingku. Temen-temen biasanya menggunakan kata “adik kelas”, “adik angkatan”, atau bahkan “kader” untuk menggambarkan junior.
Aku sendiri, cukup sering menggunakan bahasa senior dalam percakapan sehari-hari. Namun, ini hanya selera pribadi, aku biasanya cukup hati-hati dan selektif untuk mengakui diri sebagai junior seorang senior. Semisal, aku bisa dipastikan tidak akan mengakui seorang senior yang bertingkah kurang enak atau apalah, yang sekilas kurang mengenakkan. Namun, jangan ditanya jika tengah membincangkan seniorku yang berprestasi, yang keren, yang pinter, dan hal-hal baik lain, maka aku bisa saja kebablasan mengakui seorang kakak kelas sebagai seniorku. Heheheh. Curang emang, namun itulah faktanya. Aku bahkan sampai kelewat batas, yakni dengan kebiasaan terlalu membanggakan dan melebay-lebaykan senior yang hebat dan bisa tidak mengakui diri sebagai junior seorang senior yang ga ngenakin dan ga bisa dibanggakan. Hehehe.
Berangkat dari kebiasaan itu, aku juga kemudian melakukan pembatasan-pembatasan definisi dalam mengartikan senior. Misalnya dalam pergerakan. Aku akan merasa benar-benar menjadi seorang junior jika si senior pernah memberikan hal yang berarti bagiku, dari level yang paling kecil hingga level yang paling besar. Paling tidaklah, aku pernah berbincang dengannya, pernah membaca tulisannya, pernah mendengar orasinya, menyimak presentasinya, atau minimal pernah mendengar trackrecordnya. Dari situ aku belajar. Bagaimanapun, ‘keberadaan’ seorang senior, buat aku adalah sebuh keniscayaan, sebab aku dan si senior sedikit banyak menghadapi medan yang sama. Jadi, sangat tidak sia-sia jika aku belajar dari masa lalu dan sejarah, meski bukan sejarahku sendiri.
Ngomong2 soal senior, aku juga secara tanpa sengaja membuat distingsi yang cukup berbeda jauh antara senior organisasi dengan senior angkatan atau jurusan. Dipiki2 ulang, ternyata aku sering menggunakan bahasa senior dalam terminologi organisasi, sedangkan untuk menyebut senior angkatan atau jurusan, aku biasanya menggunakan bahasa kakak kelas. Distingsi ini tak ada hubungannya dengan masalah kebanggaan atau kemauan untuk mengadakan pengakuan. Hehehe. Aku terikut arus kebiasaan sepertinya, sebab di kelas, bisa dibilang jarang ada bahasa ‘senior’ untuk menunjukkan referen kakak kelas. Tidak begitu halnya dengan dunia organisasi. Di organisasi, aku lebih diakrabkan dengan bahasa senior.
Inisiatif untuk menulis catatan ini sebenarnya diawali oleh kegelisahan eksistensialis yang menderaku. Hahahahah, bahasanyaaaaaaaaaa..Jadi, sebagai mahasiswa yang uda sangat lama hidup di kampus, secara otomatis aku memiliki lebih banyak junior dibanding senior (dalam kacamatan intensitas bertemu dab berinteraksi, dll). Dari sini aku mulai merasa gerah juga. Gerah karena idealisme dan paradigmaku sendiri. Dalam pikirku, seorang senior, betapapun dengan semua keterbatasannya, harus mempertanggungjawabkan titel seniornya di depan para kader yang ia punya. Dahulu, saat masih duduk di semester bungsu, aku selalu mengidealkan sosok senior yang demikian. Makanya aku mudah banget understimate terhadap senior yang terkesan kurang mampu mempertanggungjawabkan jarak masa yang telah dilaluinya. Pikirku sederhana saja, dia uda satu tahun lebih lama mengenyam bangku kuliah dibanding aku, lha masa iya kemampuan dan wawasannya ga jauh beda ma aku?
Celakanya, paradigma itu tak banyak berubah ketika aku harus menerima gelar sebagai seorang senior. Aku merasa, aku belum dan mungkin tak akan pernah siap untuk menjadi seorang senior jika terlalu saklek melihat paragima itu. Aku bukan menafikan pandangan bahwa setiap orang memiliki sisi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak sama sekali. Aku hanya berpikir bahwa, dalam sebuah komunitas yang meski menghargai heterogenitas namun tetap mengidealkan standar yang homogen, siapapun dituntut untuk bisa memnuhi kualifikasi tertentu, yang kurang lebih sama. Dan dengan hal ini, mau tidak mau siapapun harus berusaha untuk memenuhi kualifikasi itu, seberapa berbeda bagaimanapun karakter dan kehidupannya dengan orang-orang lain.
Mudahnya, jika di kelas formal, maka standar yang harus dipenuhi adalah penguasaan materi yang memadai, presentasi yang bisa dimengerti, dan dialog yang bisa membuka dan mengeksplorasi wacana baru, dan satu lagi yang tidak termasuk dalam ranah kognitif. YAKNI MENGAYOMI ADIK KELAS. Di ranah organisasi juga begeto, tidak jauh berbeda lah..Hanya saja mungkin skill dan materi kognitif yang harus dikuasai cukup berbeda tipis. Jadi selaen bisa mengayomi, PR lain yang diemban seorang senior adalah bagaimana memberikan best performa dan best attitude plus best example bagi juniornya. Hal ini, setidaknya dapat kusimpulkan dari ilustrasi berikut,,,
Suatu hari, seorang temen korp (angkatan di organisasi) menyuruh seorang junior 2009 (berarti terpaut dua tahun dengan aku) untuk menjemput salah seorang temen sekorpku agar segera mendatangi lokasi sebuah acara. Temen yang memberikan instruksi itu—namanya Sulaiman—faham betul bahwa temen yang hendak dijemput—namanya Imam—tengah tidur selelap bayi. Jadi, hanya beban dan tanggungjawab menjadi seniorlah yang bisa membangunkannya. Tak berapa lama, junior/kader—yang bernama Iam—tampak datang dengan membawa si Imam yang masih dengan jelas mengilustrasikan kantuk yang masih menghinggapinya. Sulaiman merasa misinya sukses dan dia pun segera menghampiri Imam, menceritakan skenarionya yang sukses. Dengan gayanya yang khas, Imam berujar, “jika bukan anak 2009, aku tak akan bangun secepat ini. Coba ajah kamu nyuruh anak 2008, aku mungkin belum bangun”
Dari cerita itu, aku juga memetik sebuah pelajaran dari tabiat kehdupan manusia. Yakni bahwa, manusia, dengan keterbatasan dan keburukan seperti apapun, pasti menginginkan generasi mendatang yang lebih baik dari dirinya. Filosofi ini juga bisa aku liat dari pengabdian orangtua untuk masa depan anak-anaknya. Mulya memang, dan siapapun pasti sama-sama pernah merasakan bagaimana posisi menjadi senior dan menjadi junior. Kalo mau parno-parnoan, aku awalnya sering berpikir bahwa senior tu identik dengan sifat maunya sendiri, enaknya sendiri, nyuruh-nyuruh, sok-sokan, dan menindas junior. Meski tidak sepenuhnya salah, namun keadaan dan posisi ketika menjadi senior membuatku berpikir untuk mengubah pandangan itu. Aku tau bahwa sebejat-bejatnya senior, dia tetap menginginkan adanya kaderisasi yang bisa melahirkan kader yang jauh lebih baik dari dirinya. Hanya memang, kaderisasi dilakukan dengan cara-cara yang seniorsentris dan diterapkan pada junior yang barangkali masih asing dengan surface-surface yang sudah biasa didiami si senior.
Ya begetolah hiduuuuuuuuuup..adalah sebuah perubahan dan perkembangan yang tak akan pernah selesai. Hehehehe. Oya, kemarin, saat harus menjadi fasilitator Opak dan PKD, aku kembali dilanda ketakutan yang maha dashyat kalau-kalau aku tidak bisa mempertanggungajawabkan titelku sebagai seorang senior. Awalnya, ketika dinamika kelompok Opak, aku masih bisa mengandalkan banyak hal yang ada di otakku, seputar dunia kampus. Ngomonglah seadanya, tanpa perlu banyak konsep, tanpa perlu banyak draft, semuanya toh akan mengalir juga. Bertemu dengan orang baru, kenalan, tuker-tuker cerita dan pengalaman, dan…yaaaaa..gampanglah, bisa dikondisikan. Aku ajakin ajah mereka ngomong santae dan enaaaaak…
Namun suasanya amat sangat jauh berbeda dengan keadaan ketika PKD. Aku kelabakan saat harus mengenakan co-card sebagai fasilitator sedang tak ada sama sekali materi PKD yang aku kuasai. Untungnya, aku masih diselamatkan keadaan. Banyak temen-temenku yang bernasib sama, meski mungkin otak mereka tidak se-blank diriku. Kami pun mulai kembali belajar, menekuri modul, sharing pengetahuan dan wawasan, serta seekali bercanda. Ikon besarnya satu; BELAJAR!!!!!! Hhh,,,ya beginilah, sesal memang tak ada pernah ada di awal meski bisa diprediksikan keberadaan maupun tensinya sejak awal. Aku dan temen-temen sampai-sampai harus kembali mengikuti materi Ansos karena kurang memahami materi.
Hal yang ditakutkan sebenarnya cuma dan hanya satu. KHAWATIR ADA WACANA ATAU PERTANYAAN YANG TIDAK TERHANDLE KARENA BELUM DIPREPARE. Dan garis besarnya ya nyatanya sama, tidak mau malu di depan kader serta tidak mau memberikan contoh yang tidak baik (berupa sikap oon) terhadap kader. Yaaaaaaaaaaaaa…aku rasa itu normal adanya. Tapi ya…menjadi senior memang tak semudah yang dibayangkan, tak sesimpel yang ada di pikiran saat masih menjadi junior. Kini aku mulai belajar dan berpikir banyak untuk mendekonstruksi teori-teori kecil yang dulu aku konsep dan aku kembangkan sendiri. Hehehe. Ya, perubahan adalah suatu keniscayaan.
Dan sebagai orang yang sudah pernah mencecapi rasanya menjadi junior dan senior, aku merasa bahwa dalam keadaan bagaimanapun, manusia selalu menjadi mahluk whose middle position. Secara bersamaan, ia memiliki senior dan memiliki junior. Senior mengayominya, dan ia pun mengayomi junior. Senior memberinya contoh yang baik, ia pun harus memberi contoh yang lebih baik pada juniornya. Begitu seterusnya, salah satu siklus kehidupan manusia. Dan untuk menjadi senior ataupun junior yang baik, teorinya tidak berbeda. DO BEST AE. Dewas enough more.
Dan satu lagi, sebagai akhir tulisan ini, aku ingin mencuplik senior yang diartikan dan dianggap sebagai kependekan dari senang isteri orang oleh kalangan tertentu. Aku sendiri mendengar istilah ini pertama kali dari seorang yang…mmm..ingiiiiiiin banget aku telepon pas aku lagi bingung untuk mahami materi Ansos. Epilognya mungkin ga asik, tapi, aku sedang ingin menuli sesuatu tentang orang itu,,,jadi dipaksain dech. heheheheheh
Sangat mungkin, aku mulai akrab dengan kata tersebut ketika aku mulai masuk dalam dunia kuliah. Ketika bertemu dengan seorang yang belum pernah kutemui sebelumnya, dan katanya pernah sepondok denganku dulu, seorang teman mengatakan padaku bahwa orang tersebut adalah seniorku. Dari momen itu aku mulai menambah satu karakteristik dalam definisi senior, yakni ciri bahwa senioritas tidak harus terlalu terikat dengan kelas formal. Semisal jika ada orang yang pernah sepondok denganku namun ia tak selembaga formal denganku, maka ia juga bisa disebut seniorku, sebab kami pernah minum dari pancuran yang sama. Well, sesudah pertemuan di rektorat baru itu, aku mulai terbiasa dengan istilah senior di telingaku.
Antitesis atau mungkin lebih enak dibahasakan dengan padanan senior adalah junior. Dalam pikiran kecilku dahulu, junior adalah kata untuk merepesentasikan anak kecil. Kesimpulan itu aku dapatkan dari merk sikat gigiku, yakni pepsodent junior. Lama-lama, di lain kesempatan, ketika kakek (ayah ibuku) wafat, ada sebuah celetukan yang membuat aku kembali berpikir. Saat itu, adik tiri ibuku mengatakan bahwa adik cowoku adalah mbah kakung junior, karena face-nya yang aga sama. Dari dua momen itu, aku mulai membangun pemahaman bahwa senior-junior adalah dua padanan kata yang saling melengkapi. Seseorang bisa dikatakan senior jika dia memiliki junior. Ya…begitulah adanya.
Meski begitu, setelah beberapa saat menjalani hari-hari sebagai mahasiswa, aku merasa ada ketidaksetaraan antara intensitas pengucapan senior dan junior, minimal di lingkunganku sendiri. Senior sangat sering diucapkan, oleh orang semua kalangan bahkan. Namun tidak begitu dengan kata junior. Aku kurang terbiasa mendengar kata junior digunakan dalam percakapan di sekelilingku. Temen-temen biasanya menggunakan kata “adik kelas”, “adik angkatan”, atau bahkan “kader” untuk menggambarkan junior.
Aku sendiri, cukup sering menggunakan bahasa senior dalam percakapan sehari-hari. Namun, ini hanya selera pribadi, aku biasanya cukup hati-hati dan selektif untuk mengakui diri sebagai junior seorang senior. Semisal, aku bisa dipastikan tidak akan mengakui seorang senior yang bertingkah kurang enak atau apalah, yang sekilas kurang mengenakkan. Namun, jangan ditanya jika tengah membincangkan seniorku yang berprestasi, yang keren, yang pinter, dan hal-hal baik lain, maka aku bisa saja kebablasan mengakui seorang kakak kelas sebagai seniorku. Heheheh. Curang emang, namun itulah faktanya. Aku bahkan sampai kelewat batas, yakni dengan kebiasaan terlalu membanggakan dan melebay-lebaykan senior yang hebat dan bisa tidak mengakui diri sebagai junior seorang senior yang ga ngenakin dan ga bisa dibanggakan. Hehehe.
Berangkat dari kebiasaan itu, aku juga kemudian melakukan pembatasan-pembatasan definisi dalam mengartikan senior. Misalnya dalam pergerakan. Aku akan merasa benar-benar menjadi seorang junior jika si senior pernah memberikan hal yang berarti bagiku, dari level yang paling kecil hingga level yang paling besar. Paling tidaklah, aku pernah berbincang dengannya, pernah membaca tulisannya, pernah mendengar orasinya, menyimak presentasinya, atau minimal pernah mendengar trackrecordnya. Dari situ aku belajar. Bagaimanapun, ‘keberadaan’ seorang senior, buat aku adalah sebuh keniscayaan, sebab aku dan si senior sedikit banyak menghadapi medan yang sama. Jadi, sangat tidak sia-sia jika aku belajar dari masa lalu dan sejarah, meski bukan sejarahku sendiri.
Ngomong2 soal senior, aku juga secara tanpa sengaja membuat distingsi yang cukup berbeda jauh antara senior organisasi dengan senior angkatan atau jurusan. Dipiki2 ulang, ternyata aku sering menggunakan bahasa senior dalam terminologi organisasi, sedangkan untuk menyebut senior angkatan atau jurusan, aku biasanya menggunakan bahasa kakak kelas. Distingsi ini tak ada hubungannya dengan masalah kebanggaan atau kemauan untuk mengadakan pengakuan. Hehehe. Aku terikut arus kebiasaan sepertinya, sebab di kelas, bisa dibilang jarang ada bahasa ‘senior’ untuk menunjukkan referen kakak kelas. Tidak begitu halnya dengan dunia organisasi. Di organisasi, aku lebih diakrabkan dengan bahasa senior.
Inisiatif untuk menulis catatan ini sebenarnya diawali oleh kegelisahan eksistensialis yang menderaku. Hahahahah, bahasanyaaaaaaaaaa..Jadi, sebagai mahasiswa yang uda sangat lama hidup di kampus, secara otomatis aku memiliki lebih banyak junior dibanding senior (dalam kacamatan intensitas bertemu dab berinteraksi, dll). Dari sini aku mulai merasa gerah juga. Gerah karena idealisme dan paradigmaku sendiri. Dalam pikirku, seorang senior, betapapun dengan semua keterbatasannya, harus mempertanggungjawabkan titel seniornya di depan para kader yang ia punya. Dahulu, saat masih duduk di semester bungsu, aku selalu mengidealkan sosok senior yang demikian. Makanya aku mudah banget understimate terhadap senior yang terkesan kurang mampu mempertanggungjawabkan jarak masa yang telah dilaluinya. Pikirku sederhana saja, dia uda satu tahun lebih lama mengenyam bangku kuliah dibanding aku, lha masa iya kemampuan dan wawasannya ga jauh beda ma aku?
Celakanya, paradigma itu tak banyak berubah ketika aku harus menerima gelar sebagai seorang senior. Aku merasa, aku belum dan mungkin tak akan pernah siap untuk menjadi seorang senior jika terlalu saklek melihat paragima itu. Aku bukan menafikan pandangan bahwa setiap orang memiliki sisi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak sama sekali. Aku hanya berpikir bahwa, dalam sebuah komunitas yang meski menghargai heterogenitas namun tetap mengidealkan standar yang homogen, siapapun dituntut untuk bisa memnuhi kualifikasi tertentu, yang kurang lebih sama. Dan dengan hal ini, mau tidak mau siapapun harus berusaha untuk memenuhi kualifikasi itu, seberapa berbeda bagaimanapun karakter dan kehidupannya dengan orang-orang lain.
Mudahnya, jika di kelas formal, maka standar yang harus dipenuhi adalah penguasaan materi yang memadai, presentasi yang bisa dimengerti, dan dialog yang bisa membuka dan mengeksplorasi wacana baru, dan satu lagi yang tidak termasuk dalam ranah kognitif. YAKNI MENGAYOMI ADIK KELAS. Di ranah organisasi juga begeto, tidak jauh berbeda lah..Hanya saja mungkin skill dan materi kognitif yang harus dikuasai cukup berbeda tipis. Jadi selaen bisa mengayomi, PR lain yang diemban seorang senior adalah bagaimana memberikan best performa dan best attitude plus best example bagi juniornya. Hal ini, setidaknya dapat kusimpulkan dari ilustrasi berikut,,,
Suatu hari, seorang temen korp (angkatan di organisasi) menyuruh seorang junior 2009 (berarti terpaut dua tahun dengan aku) untuk menjemput salah seorang temen sekorpku agar segera mendatangi lokasi sebuah acara. Temen yang memberikan instruksi itu—namanya Sulaiman—faham betul bahwa temen yang hendak dijemput—namanya Imam—tengah tidur selelap bayi. Jadi, hanya beban dan tanggungjawab menjadi seniorlah yang bisa membangunkannya. Tak berapa lama, junior/kader—yang bernama Iam—tampak datang dengan membawa si Imam yang masih dengan jelas mengilustrasikan kantuk yang masih menghinggapinya. Sulaiman merasa misinya sukses dan dia pun segera menghampiri Imam, menceritakan skenarionya yang sukses. Dengan gayanya yang khas, Imam berujar, “jika bukan anak 2009, aku tak akan bangun secepat ini. Coba ajah kamu nyuruh anak 2008, aku mungkin belum bangun”
Dari cerita itu, aku juga memetik sebuah pelajaran dari tabiat kehdupan manusia. Yakni bahwa, manusia, dengan keterbatasan dan keburukan seperti apapun, pasti menginginkan generasi mendatang yang lebih baik dari dirinya. Filosofi ini juga bisa aku liat dari pengabdian orangtua untuk masa depan anak-anaknya. Mulya memang, dan siapapun pasti sama-sama pernah merasakan bagaimana posisi menjadi senior dan menjadi junior. Kalo mau parno-parnoan, aku awalnya sering berpikir bahwa senior tu identik dengan sifat maunya sendiri, enaknya sendiri, nyuruh-nyuruh, sok-sokan, dan menindas junior. Meski tidak sepenuhnya salah, namun keadaan dan posisi ketika menjadi senior membuatku berpikir untuk mengubah pandangan itu. Aku tau bahwa sebejat-bejatnya senior, dia tetap menginginkan adanya kaderisasi yang bisa melahirkan kader yang jauh lebih baik dari dirinya. Hanya memang, kaderisasi dilakukan dengan cara-cara yang seniorsentris dan diterapkan pada junior yang barangkali masih asing dengan surface-surface yang sudah biasa didiami si senior.
Ya begetolah hiduuuuuuuuuup..adalah sebuah perubahan dan perkembangan yang tak akan pernah selesai. Hehehehe. Oya, kemarin, saat harus menjadi fasilitator Opak dan PKD, aku kembali dilanda ketakutan yang maha dashyat kalau-kalau aku tidak bisa mempertanggungajawabkan titelku sebagai seorang senior. Awalnya, ketika dinamika kelompok Opak, aku masih bisa mengandalkan banyak hal yang ada di otakku, seputar dunia kampus. Ngomonglah seadanya, tanpa perlu banyak konsep, tanpa perlu banyak draft, semuanya toh akan mengalir juga. Bertemu dengan orang baru, kenalan, tuker-tuker cerita dan pengalaman, dan…yaaaaa..gampanglah, bisa dikondisikan. Aku ajakin ajah mereka ngomong santae dan enaaaaak…
Namun suasanya amat sangat jauh berbeda dengan keadaan ketika PKD. Aku kelabakan saat harus mengenakan co-card sebagai fasilitator sedang tak ada sama sekali materi PKD yang aku kuasai. Untungnya, aku masih diselamatkan keadaan. Banyak temen-temenku yang bernasib sama, meski mungkin otak mereka tidak se-blank diriku. Kami pun mulai kembali belajar, menekuri modul, sharing pengetahuan dan wawasan, serta seekali bercanda. Ikon besarnya satu; BELAJAR!!!!!! Hhh,,,ya beginilah, sesal memang tak ada pernah ada di awal meski bisa diprediksikan keberadaan maupun tensinya sejak awal. Aku dan temen-temen sampai-sampai harus kembali mengikuti materi Ansos karena kurang memahami materi.
Hal yang ditakutkan sebenarnya cuma dan hanya satu. KHAWATIR ADA WACANA ATAU PERTANYAAN YANG TIDAK TERHANDLE KARENA BELUM DIPREPARE. Dan garis besarnya ya nyatanya sama, tidak mau malu di depan kader serta tidak mau memberikan contoh yang tidak baik (berupa sikap oon) terhadap kader. Yaaaaaaaaaaaaa…aku rasa itu normal adanya. Tapi ya…menjadi senior memang tak semudah yang dibayangkan, tak sesimpel yang ada di pikiran saat masih menjadi junior. Kini aku mulai belajar dan berpikir banyak untuk mendekonstruksi teori-teori kecil yang dulu aku konsep dan aku kembangkan sendiri. Hehehe. Ya, perubahan adalah suatu keniscayaan.
Dan sebagai orang yang sudah pernah mencecapi rasanya menjadi junior dan senior, aku merasa bahwa dalam keadaan bagaimanapun, manusia selalu menjadi mahluk whose middle position. Secara bersamaan, ia memiliki senior dan memiliki junior. Senior mengayominya, dan ia pun mengayomi junior. Senior memberinya contoh yang baik, ia pun harus memberi contoh yang lebih baik pada juniornya. Begitu seterusnya, salah satu siklus kehidupan manusia. Dan untuk menjadi senior ataupun junior yang baik, teorinya tidak berbeda. DO BEST AE. Dewas enough more.
Dan satu lagi, sebagai akhir tulisan ini, aku ingin mencuplik senior yang diartikan dan dianggap sebagai kependekan dari senang isteri orang oleh kalangan tertentu. Aku sendiri mendengar istilah ini pertama kali dari seorang yang…mmm..ingiiiiiiin banget aku telepon pas aku lagi bingung untuk mahami materi Ansos. Epilognya mungkin ga asik, tapi, aku sedang ingin menuli sesuatu tentang orang itu,,,jadi dipaksain dech. heheheheheh
Hmhm...
adventure of me..
M.E.R.A.P.I
Ketika masih di Jakarta untuk suatu keperluan beberapa pekan yang lalu, aku mendengar kabar dari televisi maupun situs-situs di internet bahwa Merapi meletus. Tak berada di Jogja seperti biasanya, aku kurang begitu merasakan suasana letusan itu. Selain karena kosku cukup jauh dengan pusat bencana, aku belum pernah mengalami bencana yang bisa dibilang real disaster. Selama ini, paling mentog, aku hanya merasakan nyaliku berdetak satu-satu saat ada gempa kecil yang sekadar lewat atau sesekali pernah bertemu dengan putting beliung. Selain itu, buat aku, Jogja masihlah kota hunian yang menjanjikan. Meski banyak yang mengatakan bahwa Jogja hari ini tak seramah dulu, aku jauh lebih menyukai Jogja dibanding Surabaya, Semarang, apalagi Jakarta. Buat aku, Jogja adalah kota kecil yang masih lekat dengan nunansa ke’desa’annya.
Sebab itulah saat pertama kali mendengar bencana letusan Merapi di Jogja, aku serasa percaya tak percaya. Miris rasanya harus membayangkan kotaku akan dirundung duka. Tapi itulah yang aku liat di layar tivi maupun di situs-situs internet. Nama ‘CANGKRINGAN’ pun disebut-sebut sebagai kecamatan yang mengalami kerusakan cukup parah. Aku segera teringat bahwa beberapa hari sebelumnya, aku sempat mampir ke Cangkringan bersama temen-temen GM dalam rangka menghadiri acara PKD salah satu fakultas. Meski belum terlalu dekat dengan Merapi, tapi aku cukup merasa bahwa tempat yang saat itu aku pijaki saat ini tengah berada dalam zona bahaya.
Dan, satu hal pun berkelebart di pikirku. Beberapa hari lagi (aku lupa tanggal pastinya), aku dan teman-teman akan menghelat acara tahunan di wilayah Turi yang otomatis juga dekat—bahkan jauh lebih dekat dibanding Cangkringan—dengan Merapi. Aku tak tau bagaimana nasib dan keberlanjutan acara tersebut. Yang pasti sebelumnya, aku sudah menunggu-nunggu kapan momen itu akan tiba. Suasan Turi dan segala kekhasannya membuatku melempar ingatan pada Novemvber 2008 saat acara yang sama. Aku ingin mengulang suasana itu meski di tempat dan orang-orang yang berbeda, namun ternyata keinginan itu belum sejalan dengan kehendak Tuhan.
Lewat chating di salah satu situs jejaring sosial, seorang teman memberitahuku bahwa acara itu akan dipindah mendadak ke bagian selatan Jogja, yakni wilayah Bantul. Ya kecewa juga, pasalnya aku uda excited banged dan udah sedari dulu mengatur jadwal aku bisa stand-by di lokasi meski tidak 24 jam dalam sehari. Namun langkah memindahkan lokasi acara memang satu-satunya pilihan yang ada. Aku mungkin hanya kecewa, perasaan yang jauh amat sangat ringan dibanding temen-temen panitia dan fasilitator yang mungkin harus banyak memforsir pikiran, tenaga, serta uang. Well, setelah mendapat berita itu serta berita-berita lain di televisi, aku sadar bahwa Jogja bener-bener tengah mengkhawatirkan.
Sore, 26 Oktober, kalo ga salah, Merapi memuntahkan letusan yang cukup besar dan memakan korban jiwa maupun material. Salah satu korban jiwa yang nyawanya tidak dapat diselamatkan adalah Mbah Marijan, juru kunci atau sahibul bait Merapi. Sosok Mbah Marijan mulai dikenal sejak peristiwa letusan Merapi yang ga gitu besar pas 2006 kemarin, ketika aku belum di Jogja. Aku belum pernah bertemu dengan Mbah Marijan dan aku hanya mengenalnya melalui cerita dan catatan-catatan tentangnya. Sebab itulah aku tak banyak tau tentang sosok yang bersahaja ini.. Sebatas yang aku liat, Mbah Marijan adalah representasi dari generasi tua yang berpikir sederhana dan fokus. Fokus pada tugasnya dan filosofi hidupnya untuk’ menjaga’ Merapi dan menjadi dirinya sendiri. Simpel dan ga terlalu muluk plus ga kebanyakan request ma Tuhan. Hal itulah yang barangkali terlihat dari momen-momen ia menjemput maut di rumahnya—yang diberitakan meninggal dalam keadaan sujud ketika tengah shalat—ashar.
Terlepas dari benar-tidaknya serta besar-kecilnya kemungkinan adanya rekayasa dalam pembritaan tadi, aku menilai Mbah Marijan sebagai salah satu dari segelintir orang yang spirit hidupnya perlu dilestarikan. Simpel, sederhana, namun fokus pada apa yang menjadi spirit hidupnya. Sayang memang, sepanjang pengetahuanku, Mbah belum sempat melakukan kaderisasi pada calon penggantinya yang akan menjaga Merapi. Tapi dari itu semua, seperti kata pepatah arab, lisanul hal afshah min lisan al maqal. Perilaku dan tindak-tanduk Mbah Marijan sejauh ini—sepantasnya dan sebenere—menjadi teknik kaderisasi yang cukup baik. Masalane kemudian, bagaimana dengan kader-kader yang akan melanjutkan tugas mulia tersebut. Semoga, spirit Mbah Marijan masih akan hidup di tengah-tengah anak cucunya yang akan menjaga Jogja dan Merapi.
Selama tiga tahunan lebih di Jogja, aku sedkit banyak mengerti geografis Jogja. Jogja adalah Daerah Istimewa yang cukup mungil namun apik dengan empat kabupaten, yakni Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunung Kidul. Ada tiga hal yang mungkin menjadi ikon yang cukup identik dengan Jogja, yakni Parang Tritis (Laut Selatan tempat Bunda Nyai Roro Kidul), gunung Merapi, dan tugu. Dosenku pernah bilang bahwa ada paradigma mistis yang mengatakan, jika bisa ditarik garis lurus, maka ada garis linear antara tugu Jogja, gunung Merapi, dan Parang Tritis. So, Jogja ada di antara dua kutub, yakni kutub Selatan, Parang Tritis di Bantul, dan kutub utara yakni Merapi di Sleman. Kemarin, saat gempa Jogja, daerah Selatan mengalami kerusakan cukup parah. Dan hari ini, saat Merapi meletus, daerah Utara Jogja serta kabupaten lain yang berbatasan dengan Jogja (seperti Magelang dan Boyolali) harus sejenak menjadi kota mati.
Jadi, dari perhitungan sederhana semacam itu, malam itu, ketika hujan Pasir sampai di tempatku, aku berinisiatif untuk mencari suaka dan perlindungan (baca: pengunsian) ke arah selatan, Bantul atau Wonosari. Saat aku menghubungi seorang temen via telepon, dia mengatakan bahwa Wonosari menjadi final destination dari masyarakat yang harus dievakuasi. Saat itu, uda lewat tengah malam, aku sudah sampai di Jalan Wonosari, namun aku mengurungkan niat untuk terus naik karena medan yang cukup berat tidak akan mau berkompromi dengan mataku yang cukup mengantuk dan aku yang kelelahan, meski sehabis bangun tidur. Malam—atau dini hari dan pagi itu—menjadi momoen yang cukup menegangkan buat aku, barangkali karena momen pertama.
5 November waktu itu. Aku inget banget, tidurku lelap banget dan banget lelap, sebab seharian aku kecapean mempersiapkan makalah yang harus aku presentasikan besok di kelas Filsafat Bahasa. Ga tau jam berapa pastinya, temen kamarku membangunkanku dan langsung berucap banyak hal. Di luar, suasana sudah ramai. Temen-temen kos pada bangun dan semuanya merengsek ke depan televisi untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Aku masih males beranjak dari tempat tidur dan segera mencari hape yang biasanya jadi barang terakhir yang aku liat sebelum aku memutuskan untuk terlelap. Ada banyak panggilan dan beberapa sms yang intinya sama, menyuruhku untuk bangun dan mengabari bahwa kotaku tengah dilanda hujan pasir, setelah Merapi kembali meletus. Aku bener-bener panik dan kantuk lelahku hilang seketika.
Aku langsung menghubungi beberapa nomor di hapeku. Ksatria, Bapak dan Umik, Mbk Rom, serta Unyil. Minimal, orang-orang itulah yang barangkali paling banyak menyita waktu dan tempatku belakangan ini. So, aku langsung mengabari dan mengontak mereka. Dial pertama, ksatria. Dia sudah terjaga dan menyadari bahwa hujan pasir juga tengah mengguyur genting-genting kamar kecilnya. Mbak Rom, Bapakku, dan Unyil masih terlelap. Panggilan teleponku lah yang membangunkan mereka. Aku bicara seperlunya dan tetap berusaha mengkondisikan diri setenang mungkin di keadaan yang cukup genting itu. (Saat itu aku masih sempat berpikir bahwa ada satu nomor yang seharusnya juga aku dial, sekadar memberitau suara di sana bahwa aku tengah berada dalam keadaan aga genting. Tapi, aku memang wajib mengurungkan niat itu dan menganggap pikiran itu tidak pernah muncul. Bukan waktu yang tepat untuk bermain dengan perasaan)
Setelah mengumpulkan sukma dan kesadaran, aku bergegas ke depan tivi untuk bergabung dengan temen-temen kos. Di sana, sudah cukup banyak teman yang tampak terjaga sedari tadi. Pemberitaan di televisi, selain informatif, ternyata juga mengandung unsur lebay. Entah, apakah unsur ini memang harus ada dalam sebuah pemberitaan demi alasan pasar, yang pasti aku merasa pemberitaan dini hari itu cukup berlebihan. Apalgi jika konsumen berita itu adlah orang tua yang anaknya kuliah/skolah di Jogja. Bisa dibayangkan bagamana panik dan hebohnya.
Terkait dengan sisi lebay media itu, aku punya berbagai cerita dari penuturan temen-temenku. Yang pertama, dari salah satu temen yang menuturkan bahwa orangtuanya rela mengeluarkan kocek setengah juta lebih untuk membayar taksi yang membawa ketiga anaknya pulang dari Jogja menuju Banjarnegara. Yang kedua, seorang temenku yang lain memutuskan untuk mudik setelah ada pengumuman libur dari kampus. Ketika nyampai rumah, sang ibu menyambut temenku dengan penuh perasaan dan keharuan, hingga temenku tersebut membahasakan dengan “seperti menjemput orang dateng berhaji dari Mekkah” plus pake acara memeluk sambil menangis. Dan yang ketiga, cerita lain, seorang ibu yang tiga anaknya sama-sama belajar di Jogjakarta, dijauhkan dari televisi dan siara berita agar tidak berlebihan mengkhawatirkan keberadaan anaknya.
Semua ekspresi itu, memang murni berangkat dari rasa sayang dan kekahawatiran orang tua (terutama orang tua perempuan) terhadap anak-anaknya. Tapi yaaaa..mereka yang tidak tinggal di Jogja dan melihat pemberitaan yang tampak demikian heboh dan darurat, bisa dipasatikan akan berekspresi demikian. Wajarlah, adanya. Dalam menghadapi situasi yang cukup dilematis ini, langkah teraman yang aku ambil adalah dengan meyakinkan orang tuaku (bapak dan terutama umik) bahwa keadaanku di sini tidaklah segaswat seperti keadaan yang diberitakan di televisi. Aku juga berkali-kali mengatakan bahwaaa…tempat aku kos maupun tempat aku kuliah berada adalam radius yang amat banget jauh dengan lokaso bencana. Banyak lah, yang aku ucapkan berkali-kali kepada orangtuaku untuk meminimalisir kekhawatiran beliau-beliau. Well, above all, aku sudah cukup tua dan tanggap bencana untuk menyelamatkan diri sebisa mungkin. So, beliau tidak perlu mengkahawatirkanku terlalu berlebihan.
Selain orang tuaku, beberapa keluarga dan teman dekat juga selalu mengupdate suasana di Jogja, khususnya keadaanku sendiri. Meski kadang males mengangkat telepon dan membalas sms yang cukup banyak itu, aku merasa senang juga diperhatikan orang-orang yang aku sayangi dan pernah seruang dan sewaktu denganku, dahulu, di berbagai tempat dan berbagai alasan. Hehehehe. Karena paradigma ini pulalah, aku kadang protes pada temen dekat yang tidak menanyakan kabarku dengan sms yang sok manja banget, “Kau tak mengkhawatirkanku?” Heheheh..Pede banget emang, tapi aku hanya ingin mencari suasana lain di balik kondisi gempa yang cukup meresahkan dan melelahkan ini. Setidaknya, dari suasana ini juga, aku bisa tau mana temen-temenku yang memiliki rasa sayang dan peduli dengan ekspresi kekhawatiran, sindrom yang barangkali juga menjangkitiku. Hehehe. Jadi, setelah menemukan temen sealiran, aku lebih mudah mengenali gejala ini. Ga nyambung ah. Hahahaha
Selaen hujan pasir, aku juga pernah merasakan hujan air..hehehe..maksudnya hujan abu. Hujan abu ma hujan pasir sebenernya ga jauh beda. Sama-sama mengharuskan warga Jogja untuk mengenakan masker. Hujan abu..pertama kali mengguyur daerah kosku di suatu pagi, sehari setelah aku mendarat di Jogja. Bedane, hujan pasir sedikit lebih menyeramkan dibanding hujan abu. Jika ketika abu, genting kos tak berdecit dan tak menimbulkan suara apa-apa, maka saat hujan pasir datang, serasa ada irama tak beraturan yang menghinggapi atap-atap kos dan membuat penghuninya dua kali lebih resah dan lebih cemas dibanding ketika hujan abu tengah mengguyur. Semoga, hanya hujan abu dan hujan pasir yang sudi menghinggapi kota dan kosku, tidak sampai hujan kerikil apalag nomaden goat (wedhus gembel).
Untuk merapi, meski tak terprediksi, semoga bisa mengerti. Amien.
Sebab itulah saat pertama kali mendengar bencana letusan Merapi di Jogja, aku serasa percaya tak percaya. Miris rasanya harus membayangkan kotaku akan dirundung duka. Tapi itulah yang aku liat di layar tivi maupun di situs-situs internet. Nama ‘CANGKRINGAN’ pun disebut-sebut sebagai kecamatan yang mengalami kerusakan cukup parah. Aku segera teringat bahwa beberapa hari sebelumnya, aku sempat mampir ke Cangkringan bersama temen-temen GM dalam rangka menghadiri acara PKD salah satu fakultas. Meski belum terlalu dekat dengan Merapi, tapi aku cukup merasa bahwa tempat yang saat itu aku pijaki saat ini tengah berada dalam zona bahaya.
Dan, satu hal pun berkelebart di pikirku. Beberapa hari lagi (aku lupa tanggal pastinya), aku dan teman-teman akan menghelat acara tahunan di wilayah Turi yang otomatis juga dekat—bahkan jauh lebih dekat dibanding Cangkringan—dengan Merapi. Aku tak tau bagaimana nasib dan keberlanjutan acara tersebut. Yang pasti sebelumnya, aku sudah menunggu-nunggu kapan momen itu akan tiba. Suasan Turi dan segala kekhasannya membuatku melempar ingatan pada Novemvber 2008 saat acara yang sama. Aku ingin mengulang suasana itu meski di tempat dan orang-orang yang berbeda, namun ternyata keinginan itu belum sejalan dengan kehendak Tuhan.
Lewat chating di salah satu situs jejaring sosial, seorang teman memberitahuku bahwa acara itu akan dipindah mendadak ke bagian selatan Jogja, yakni wilayah Bantul. Ya kecewa juga, pasalnya aku uda excited banged dan udah sedari dulu mengatur jadwal aku bisa stand-by di lokasi meski tidak 24 jam dalam sehari. Namun langkah memindahkan lokasi acara memang satu-satunya pilihan yang ada. Aku mungkin hanya kecewa, perasaan yang jauh amat sangat ringan dibanding temen-temen panitia dan fasilitator yang mungkin harus banyak memforsir pikiran, tenaga, serta uang. Well, setelah mendapat berita itu serta berita-berita lain di televisi, aku sadar bahwa Jogja bener-bener tengah mengkhawatirkan.
Sore, 26 Oktober, kalo ga salah, Merapi memuntahkan letusan yang cukup besar dan memakan korban jiwa maupun material. Salah satu korban jiwa yang nyawanya tidak dapat diselamatkan adalah Mbah Marijan, juru kunci atau sahibul bait Merapi. Sosok Mbah Marijan mulai dikenal sejak peristiwa letusan Merapi yang ga gitu besar pas 2006 kemarin, ketika aku belum di Jogja. Aku belum pernah bertemu dengan Mbah Marijan dan aku hanya mengenalnya melalui cerita dan catatan-catatan tentangnya. Sebab itulah aku tak banyak tau tentang sosok yang bersahaja ini.. Sebatas yang aku liat, Mbah Marijan adalah representasi dari generasi tua yang berpikir sederhana dan fokus. Fokus pada tugasnya dan filosofi hidupnya untuk’ menjaga’ Merapi dan menjadi dirinya sendiri. Simpel dan ga terlalu muluk plus ga kebanyakan request ma Tuhan. Hal itulah yang barangkali terlihat dari momen-momen ia menjemput maut di rumahnya—yang diberitakan meninggal dalam keadaan sujud ketika tengah shalat—ashar.
Terlepas dari benar-tidaknya serta besar-kecilnya kemungkinan adanya rekayasa dalam pembritaan tadi, aku menilai Mbah Marijan sebagai salah satu dari segelintir orang yang spirit hidupnya perlu dilestarikan. Simpel, sederhana, namun fokus pada apa yang menjadi spirit hidupnya. Sayang memang, sepanjang pengetahuanku, Mbah belum sempat melakukan kaderisasi pada calon penggantinya yang akan menjaga Merapi. Tapi dari itu semua, seperti kata pepatah arab, lisanul hal afshah min lisan al maqal. Perilaku dan tindak-tanduk Mbah Marijan sejauh ini—sepantasnya dan sebenere—menjadi teknik kaderisasi yang cukup baik. Masalane kemudian, bagaimana dengan kader-kader yang akan melanjutkan tugas mulia tersebut. Semoga, spirit Mbah Marijan masih akan hidup di tengah-tengah anak cucunya yang akan menjaga Jogja dan Merapi.
Selama tiga tahunan lebih di Jogja, aku sedkit banyak mengerti geografis Jogja. Jogja adalah Daerah Istimewa yang cukup mungil namun apik dengan empat kabupaten, yakni Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunung Kidul. Ada tiga hal yang mungkin menjadi ikon yang cukup identik dengan Jogja, yakni Parang Tritis (Laut Selatan tempat Bunda Nyai Roro Kidul), gunung Merapi, dan tugu. Dosenku pernah bilang bahwa ada paradigma mistis yang mengatakan, jika bisa ditarik garis lurus, maka ada garis linear antara tugu Jogja, gunung Merapi, dan Parang Tritis. So, Jogja ada di antara dua kutub, yakni kutub Selatan, Parang Tritis di Bantul, dan kutub utara yakni Merapi di Sleman. Kemarin, saat gempa Jogja, daerah Selatan mengalami kerusakan cukup parah. Dan hari ini, saat Merapi meletus, daerah Utara Jogja serta kabupaten lain yang berbatasan dengan Jogja (seperti Magelang dan Boyolali) harus sejenak menjadi kota mati.
Jadi, dari perhitungan sederhana semacam itu, malam itu, ketika hujan Pasir sampai di tempatku, aku berinisiatif untuk mencari suaka dan perlindungan (baca: pengunsian) ke arah selatan, Bantul atau Wonosari. Saat aku menghubungi seorang temen via telepon, dia mengatakan bahwa Wonosari menjadi final destination dari masyarakat yang harus dievakuasi. Saat itu, uda lewat tengah malam, aku sudah sampai di Jalan Wonosari, namun aku mengurungkan niat untuk terus naik karena medan yang cukup berat tidak akan mau berkompromi dengan mataku yang cukup mengantuk dan aku yang kelelahan, meski sehabis bangun tidur. Malam—atau dini hari dan pagi itu—menjadi momoen yang cukup menegangkan buat aku, barangkali karena momen pertama.
5 November waktu itu. Aku inget banget, tidurku lelap banget dan banget lelap, sebab seharian aku kecapean mempersiapkan makalah yang harus aku presentasikan besok di kelas Filsafat Bahasa. Ga tau jam berapa pastinya, temen kamarku membangunkanku dan langsung berucap banyak hal. Di luar, suasana sudah ramai. Temen-temen kos pada bangun dan semuanya merengsek ke depan televisi untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Aku masih males beranjak dari tempat tidur dan segera mencari hape yang biasanya jadi barang terakhir yang aku liat sebelum aku memutuskan untuk terlelap. Ada banyak panggilan dan beberapa sms yang intinya sama, menyuruhku untuk bangun dan mengabari bahwa kotaku tengah dilanda hujan pasir, setelah Merapi kembali meletus. Aku bener-bener panik dan kantuk lelahku hilang seketika.
Aku langsung menghubungi beberapa nomor di hapeku. Ksatria, Bapak dan Umik, Mbk Rom, serta Unyil. Minimal, orang-orang itulah yang barangkali paling banyak menyita waktu dan tempatku belakangan ini. So, aku langsung mengabari dan mengontak mereka. Dial pertama, ksatria. Dia sudah terjaga dan menyadari bahwa hujan pasir juga tengah mengguyur genting-genting kamar kecilnya. Mbak Rom, Bapakku, dan Unyil masih terlelap. Panggilan teleponku lah yang membangunkan mereka. Aku bicara seperlunya dan tetap berusaha mengkondisikan diri setenang mungkin di keadaan yang cukup genting itu. (Saat itu aku masih sempat berpikir bahwa ada satu nomor yang seharusnya juga aku dial, sekadar memberitau suara di sana bahwa aku tengah berada dalam keadaan aga genting. Tapi, aku memang wajib mengurungkan niat itu dan menganggap pikiran itu tidak pernah muncul. Bukan waktu yang tepat untuk bermain dengan perasaan)
Setelah mengumpulkan sukma dan kesadaran, aku bergegas ke depan tivi untuk bergabung dengan temen-temen kos. Di sana, sudah cukup banyak teman yang tampak terjaga sedari tadi. Pemberitaan di televisi, selain informatif, ternyata juga mengandung unsur lebay. Entah, apakah unsur ini memang harus ada dalam sebuah pemberitaan demi alasan pasar, yang pasti aku merasa pemberitaan dini hari itu cukup berlebihan. Apalgi jika konsumen berita itu adlah orang tua yang anaknya kuliah/skolah di Jogja. Bisa dibayangkan bagamana panik dan hebohnya.
Terkait dengan sisi lebay media itu, aku punya berbagai cerita dari penuturan temen-temenku. Yang pertama, dari salah satu temen yang menuturkan bahwa orangtuanya rela mengeluarkan kocek setengah juta lebih untuk membayar taksi yang membawa ketiga anaknya pulang dari Jogja menuju Banjarnegara. Yang kedua, seorang temenku yang lain memutuskan untuk mudik setelah ada pengumuman libur dari kampus. Ketika nyampai rumah, sang ibu menyambut temenku dengan penuh perasaan dan keharuan, hingga temenku tersebut membahasakan dengan “seperti menjemput orang dateng berhaji dari Mekkah” plus pake acara memeluk sambil menangis. Dan yang ketiga, cerita lain, seorang ibu yang tiga anaknya sama-sama belajar di Jogjakarta, dijauhkan dari televisi dan siara berita agar tidak berlebihan mengkhawatirkan keberadaan anaknya.
Semua ekspresi itu, memang murni berangkat dari rasa sayang dan kekahawatiran orang tua (terutama orang tua perempuan) terhadap anak-anaknya. Tapi yaaaa..mereka yang tidak tinggal di Jogja dan melihat pemberitaan yang tampak demikian heboh dan darurat, bisa dipasatikan akan berekspresi demikian. Wajarlah, adanya. Dalam menghadapi situasi yang cukup dilematis ini, langkah teraman yang aku ambil adalah dengan meyakinkan orang tuaku (bapak dan terutama umik) bahwa keadaanku di sini tidaklah segaswat seperti keadaan yang diberitakan di televisi. Aku juga berkali-kali mengatakan bahwaaa…tempat aku kos maupun tempat aku kuliah berada adalam radius yang amat banget jauh dengan lokaso bencana. Banyak lah, yang aku ucapkan berkali-kali kepada orangtuaku untuk meminimalisir kekhawatiran beliau-beliau. Well, above all, aku sudah cukup tua dan tanggap bencana untuk menyelamatkan diri sebisa mungkin. So, beliau tidak perlu mengkahawatirkanku terlalu berlebihan.
Selain orang tuaku, beberapa keluarga dan teman dekat juga selalu mengupdate suasana di Jogja, khususnya keadaanku sendiri. Meski kadang males mengangkat telepon dan membalas sms yang cukup banyak itu, aku merasa senang juga diperhatikan orang-orang yang aku sayangi dan pernah seruang dan sewaktu denganku, dahulu, di berbagai tempat dan berbagai alasan. Hehehehe. Karena paradigma ini pulalah, aku kadang protes pada temen dekat yang tidak menanyakan kabarku dengan sms yang sok manja banget, “Kau tak mengkhawatirkanku?” Heheheh..Pede banget emang, tapi aku hanya ingin mencari suasana lain di balik kondisi gempa yang cukup meresahkan dan melelahkan ini. Setidaknya, dari suasana ini juga, aku bisa tau mana temen-temenku yang memiliki rasa sayang dan peduli dengan ekspresi kekhawatiran, sindrom yang barangkali juga menjangkitiku. Hehehe. Jadi, setelah menemukan temen sealiran, aku lebih mudah mengenali gejala ini. Ga nyambung ah. Hahahaha
Selaen hujan pasir, aku juga pernah merasakan hujan air..hehehe..maksudnya hujan abu. Hujan abu ma hujan pasir sebenernya ga jauh beda. Sama-sama mengharuskan warga Jogja untuk mengenakan masker. Hujan abu..pertama kali mengguyur daerah kosku di suatu pagi, sehari setelah aku mendarat di Jogja. Bedane, hujan pasir sedikit lebih menyeramkan dibanding hujan abu. Jika ketika abu, genting kos tak berdecit dan tak menimbulkan suara apa-apa, maka saat hujan pasir datang, serasa ada irama tak beraturan yang menghinggapi atap-atap kos dan membuat penghuninya dua kali lebih resah dan lebih cemas dibanding ketika hujan abu tengah mengguyur. Semoga, hanya hujan abu dan hujan pasir yang sudi menghinggapi kota dan kosku, tidak sampai hujan kerikil apalag nomaden goat (wedhus gembel).
Untuk merapi, meski tak terprediksi, semoga bisa mengerti. Amien.
Hmhm...
adventure of me..
Tanpa Judul Ae
Disebut surat mungkin kurang tepat, dikatakan puisi juga tidak pas. Karangan ringan aja sebenre, sebuah karangan yang akan memaparkan sekelumit kisah tentang seseorang. Tak berat dan tak rumit.
Sesederhana itu pulalah mahluk bernama rindu, barangkali. Rindu sebenernya ya tidak perlu terlalu dibuat ribet dan rumit. Biasa ae dan seharusnya disikapi biasa aja. Idealnya gitu, dan wacanan memang amat sangat lebih mudah dibanding kepanjangan tangan wacana tersebut. Btw-btw, belum ada regulasi yang melarang seseorang untuk merindukan siapa dan apapun yang dikehendakinya. So, rindu boleh aja, asal jangan gila-gilaan. Oooppss, emang seperti apakah rindu yang gila-gilaan? Intine rindu yang ga sehat ae laaaaaaaaaah…
Dan pada diriku sekarang, what yearning I have? And how should it be? Pertanyaan yang sebenere gampang banget untuk dijawab. Tapi ya embuhlah, aku uda mulai dulu merasa kewalahan dan hampir merasa ga kuat untuk berjibaku dengan makhluk bernama rindu. Ga gitu ganas, tapi efeknya cukup mematikan. Bagaimana tidak, hampir tidak ada satu pun teori yang bisa secara saklek memetakan bagaimana ia adanya dan bagaimana ia hidup dan berkembang. Seperti, gejala pertama yang aku kenali adalah…bahwa Rindu tak harus bertemu.
Ya, bener. Gejala itu juga menjangkitiku. Aku merindukan seseorang namun aku emoh untuk bertemu dengannya. Aku tak berwacana belaka dengan pernyataanku tadi. Murni, itulah yang kurasakan. Agaknya aku mulai berpikir bahwaa…bertemu bukanlah satu-satunya penangkal atau solusi yang solutif atas mahluk bernama rindu. Orang lain barangkali ada yang merasakan seperti yang aku alami saat ini, hanya mungkin motif dan alurnya berbeda. Dan untuk kasusku sekarang, aku mulai berpikir bahwaaaaaaaa…Ada satu alasan besar mengapa aku tak ingin menebus rinduku dengan ritual semacam pertemuan kopi darat atau cengkerama digital..
Lagi-lagi aku menganggapnya sebagai suatu hal yang sederhana dan amat simpel. Aku tak ingin menebus rindu yang menumpuk itu dengan pertemuan sebab aku pun mulai yakin, bahwa material yang aku rindukan tidak lagi bisa seruang dan sewaktu bersamaku. Ia semacam hidup dalam kenangan manis yang telah usai dan tidak akan pernah terulang lagi sampai kapanpun, dengan orang yang sama maupun orang yang berbeda. Wujudnya masihlah ada dan empiris, hanya saja jiwa dan segala kenangan tentangnya terasa telah menjadi sebuah metafisika bagikuuuu.. Sebab itulah aku berpikir positivistik ajah, tak mau menghampiri metafisika yang jelas-jelas tidak empirik dan tidak berwujud. Jadi, jalan keluarnya, biarlah rindu itu menumpuk dan menemukan riwayatnya dengan natural, tanpa harus ada ritual-ritual pertamuan yang terkadang hanya menyakitkan. Hahahahahahahaaaaaaaaaaa…MELOOOOOOOOOW…
Berangkat dari semangat dan kesadaran itu, aku jadi lebih berpikir banyak tentang perasaan, keinginan, juga mungkin egoismeku. Dan kontemplasi ga jelas itu kemudian mengantarkanku pada gejala yang kedua. Gejala rindu gila yang kedua. Yakni bahwa, rindu pada seseorang tidak hanya akan kembali memflashback ingatan pada episode2 kehidupan sebelumnya, namun juga memberi banyak pintu untuk kembali berpikir. Kembali merenungkan berbagai persitiwa, bermacam proses, serentetan kenangan, dan beberapa hal yang mungkin akan sedikit banyak mengubah persepsi kita tentang orang yang tengah menjadi referen dari semua perenungan dan kenangan-kenangan masa lalu itu…
Dalam fase-fase inilah, seprti yang kurasakan, terbuka amat sangat banyak kemungkinan seseorang akan menydari betapa berharganya momen, kenangan, dan jiwa yang sudah lewat dan tak akan kembali tersebut. Kita bisa tertawa sendiri, menangis sendiri, malu-malu sendiri, dan segala hal yang barangkali bisa membuat kita lebih bijak dan lebih arif memandang kehidupan dan semua akseseorisnya. Dalam kasusku, lagi-lagi, yang ingin aku tuturkan hanyalah bahwa dalam momen tersebut, aku baru menyadari bahwaaaaaaaa..arti seseorang—you know who—yang tak akan pernah menampakkan dirinya kembali lagi tersebut amat banget terasaaaaaaaaa….Betapa tanpa skenario Tuhan yang mempertemukan aku dengannya, aku nyaris tidak mungkin menjadi ITA hari ini…
Dan malam ini, berlomba dengan denyit-denyit keyboard yang mulai kelelahan, rinduku berdentam pelan-pelan. Iramanya relatif stabil, sebab aku sudah sedari dulu merancang banyak hal agar irama dan ritme rinduku tidak sefluktuatif perasaanku. Sayang memang, langkah konkret itu harus aku lakukan dengan hal yang sebenarnya kurang masuk akal dan sangat tidak mengenakkn; Bersandiwara. Pura-pura tak punya rindu, pura-pura tak ada kangen, dan berlagak seakan semuanya baik-baik saja padahal aku tengah menyumbat mulut luka yang mengaga bersama perihnya yang merngaroma… Aku bahkan dengan rasa tega yang penuh meski dengan amat berat hati sudah menutup akses alasanku untuk bisa bertemu dengan dia—you know who—yang sebenernya menjadi muara dari semua rinduku.
Dalam perhitunganku, ketika akses-akses alasan itu sudah aku blokir, aku tak lagi perlu risau menunggu waktu bisa kembalikan masa-masa indah yang pernah melenakanku itu. Aku tak perlu lagi menunggu apakah ada kabar dari masa lalu yang akan kembali melemparkanku pada surga sementaranya. Aku meneguhkan hati—meski sampe sekarang belum teguh-teguh, ehehehehe—bahwa,,,akhir dari episode panjng yang aku jalani haruslah berujung pada keikhlasan…Biarlah ikhlas yang masih mati-matian aku pelajari ini menjadi ikon yang manis dari semua episode yang juga,,,hhh,,,too sweet to forget…Paling tidak, aku harus berpikir ulang SERIBU SERATUS KALI untuk mencabut ucapanku, menjilati lidah yang sudah aku buang, dan membuka jalur akses alasan yang sudah aku dirikan semenjulang mungkin.
Rindu mengajarkan banyak hal, semisal bersyukur atas momen dan anugerah yang sudah berlalu, bagaimana mengikhlaskan banyak hal dan menjadikannya tambang hikmah yang tak akan habis digali, namun rindu ternyata licik juga. Aku merasakan hal ini utamanya dalam hal…apologinya yang terlalu berlebihan. Entah, percaya atau tidak, sudah pernah atau belum pernah kaualami, aku rasa rindu menjadi rezim paling otoriter yang bisa dengan mudah memasukkan ‘intervensi’ seseorang ke dalam semua lini kehidupan. Mudahnya, tak jauh beda dengan salah satu lirik yang dinyanyikan Avril Lavigne, everything that I do, reminds me of youu….Dan lirik itu bukan hanya wacana yang mengawang-ngawang, Saudara-saudara!!!!!!
Aku merasakan, mengalami, dan menyaksikannya sendiri. Meski latar belakang rinduku memang support, namun aku bisa memprediksi bahwa gejala ini tak hanya menjangkitiku. Ya, pernahkah Kau merasakan bahwa ketika Kau merindukan seseorang, dia bisa hadir di setiap tempat yang pijak dan setiap waktu yang kau temui? Pada semua keadaan yang melibatkanmu, pada setiap suasana yang menjadi rutinitasmu, dan semuanya. Di setiap denyut pikiran, di setiap jengkal tempat, di semua perasaan, dan dalam 24 jam sehari serta 7 hari sepekan. Dalam hal ini, mau tidak mau, apologi yang berlebihan menjadi salah satu komponen yang akan mendukung suksesi gejala ketiga ini.
Ngeselin emang, tapi rasa rindu berikut gejala-gejalanya—yang barangkali akan sangat amat berbeda di antara masing-masing orang—adalah suatu hal yang alami an-sich dan amt sangat natural. Jadi, mustahil rasanya untuk bisa menghindar dan berlari. Aku sendiri, hingga hari ini, masih percaya, bahwa rindu akan menemukan bentuk dan riwayatnya sendiri, bersama teka-teki yang akan disingkap oleh sang waktu…
Untuk seseorang yang berada di balik pikiran dan perasaanku ketika menulis ini, aku ingin…ingin sekali mengulang kembali semua momen-momen yang tak akan datang kembali lagi. Momen bersamamu, momen mengenalmu, momen menghujatmu, momen memujamu, momen menghawatirkanmu, dan saat ini, momoen merindukanmu adalah rentetan-rentetan proses yang banyak banget berandil dalam membentuk keseluruhan diriku. Aku sama sekali tak pernah berpikir bahwa…Aku akan merindukanku segila ini, akan menyanyangimu setakterdefinisi ini…
Kalaupun kau pasti tidak akan kembali—karena aku harus selalu memastikan bahwa aku benar-benar pergi dari hidupmu—aku masih menaruh harap di batas putus asaku yang paling dalam, untuk kembali merasakan energi-energi yang sering kaupekikkan di telinga tuliku. Tidak untuk memintamu kembali datang dan bertandang, namun untuk mengabadikan sosok dan kenangan bersamamu dalam memoriku yang tak akan pernah terhapus oleh apapun…
Malam ini, atau mungkin pagi ini, aku kembali rindu pada segenapmu. Rindu pada perdebatan panjang kita yang kebanyakan tak berujung-pangkal, rindu pada diammu yang tak pernah mau aku bobol, rindu pada optimismemu, dan yang pasti, aku rindu caramu mencintaiku dan membuatku tak lagi merasa bahwa engkau adalah orang lain. Aku rindu malam-malam panjang ituuu…Jika saja kau baca tulisan ini, kau mungkin akan tau, aku kembali menangis, untuk dan karenamu. Selamat tidur, lelaplah di hatiku.
*) Written on 09-10-10
Sesederhana itu pulalah mahluk bernama rindu, barangkali. Rindu sebenernya ya tidak perlu terlalu dibuat ribet dan rumit. Biasa ae dan seharusnya disikapi biasa aja. Idealnya gitu, dan wacanan memang amat sangat lebih mudah dibanding kepanjangan tangan wacana tersebut. Btw-btw, belum ada regulasi yang melarang seseorang untuk merindukan siapa dan apapun yang dikehendakinya. So, rindu boleh aja, asal jangan gila-gilaan. Oooppss, emang seperti apakah rindu yang gila-gilaan? Intine rindu yang ga sehat ae laaaaaaaaaah…
Dan pada diriku sekarang, what yearning I have? And how should it be? Pertanyaan yang sebenere gampang banget untuk dijawab. Tapi ya embuhlah, aku uda mulai dulu merasa kewalahan dan hampir merasa ga kuat untuk berjibaku dengan makhluk bernama rindu. Ga gitu ganas, tapi efeknya cukup mematikan. Bagaimana tidak, hampir tidak ada satu pun teori yang bisa secara saklek memetakan bagaimana ia adanya dan bagaimana ia hidup dan berkembang. Seperti, gejala pertama yang aku kenali adalah…bahwa Rindu tak harus bertemu.
Ya, bener. Gejala itu juga menjangkitiku. Aku merindukan seseorang namun aku emoh untuk bertemu dengannya. Aku tak berwacana belaka dengan pernyataanku tadi. Murni, itulah yang kurasakan. Agaknya aku mulai berpikir bahwaa…bertemu bukanlah satu-satunya penangkal atau solusi yang solutif atas mahluk bernama rindu. Orang lain barangkali ada yang merasakan seperti yang aku alami saat ini, hanya mungkin motif dan alurnya berbeda. Dan untuk kasusku sekarang, aku mulai berpikir bahwaaaaaaaa…Ada satu alasan besar mengapa aku tak ingin menebus rinduku dengan ritual semacam pertemuan kopi darat atau cengkerama digital..
Lagi-lagi aku menganggapnya sebagai suatu hal yang sederhana dan amat simpel. Aku tak ingin menebus rindu yang menumpuk itu dengan pertemuan sebab aku pun mulai yakin, bahwa material yang aku rindukan tidak lagi bisa seruang dan sewaktu bersamaku. Ia semacam hidup dalam kenangan manis yang telah usai dan tidak akan pernah terulang lagi sampai kapanpun, dengan orang yang sama maupun orang yang berbeda. Wujudnya masihlah ada dan empiris, hanya saja jiwa dan segala kenangan tentangnya terasa telah menjadi sebuah metafisika bagikuuuu.. Sebab itulah aku berpikir positivistik ajah, tak mau menghampiri metafisika yang jelas-jelas tidak empirik dan tidak berwujud. Jadi, jalan keluarnya, biarlah rindu itu menumpuk dan menemukan riwayatnya dengan natural, tanpa harus ada ritual-ritual pertamuan yang terkadang hanya menyakitkan. Hahahahahahahaaaaaaaaaaa…MELOOOOOOOOOW…
Berangkat dari semangat dan kesadaran itu, aku jadi lebih berpikir banyak tentang perasaan, keinginan, juga mungkin egoismeku. Dan kontemplasi ga jelas itu kemudian mengantarkanku pada gejala yang kedua. Gejala rindu gila yang kedua. Yakni bahwa, rindu pada seseorang tidak hanya akan kembali memflashback ingatan pada episode2 kehidupan sebelumnya, namun juga memberi banyak pintu untuk kembali berpikir. Kembali merenungkan berbagai persitiwa, bermacam proses, serentetan kenangan, dan beberapa hal yang mungkin akan sedikit banyak mengubah persepsi kita tentang orang yang tengah menjadi referen dari semua perenungan dan kenangan-kenangan masa lalu itu…
Dalam fase-fase inilah, seprti yang kurasakan, terbuka amat sangat banyak kemungkinan seseorang akan menydari betapa berharganya momen, kenangan, dan jiwa yang sudah lewat dan tak akan kembali tersebut. Kita bisa tertawa sendiri, menangis sendiri, malu-malu sendiri, dan segala hal yang barangkali bisa membuat kita lebih bijak dan lebih arif memandang kehidupan dan semua akseseorisnya. Dalam kasusku, lagi-lagi, yang ingin aku tuturkan hanyalah bahwa dalam momen tersebut, aku baru menyadari bahwaaaaaaaa..arti seseorang—you know who—yang tak akan pernah menampakkan dirinya kembali lagi tersebut amat banget terasaaaaaaaaa….Betapa tanpa skenario Tuhan yang mempertemukan aku dengannya, aku nyaris tidak mungkin menjadi ITA hari ini…
Dan malam ini, berlomba dengan denyit-denyit keyboard yang mulai kelelahan, rinduku berdentam pelan-pelan. Iramanya relatif stabil, sebab aku sudah sedari dulu merancang banyak hal agar irama dan ritme rinduku tidak sefluktuatif perasaanku. Sayang memang, langkah konkret itu harus aku lakukan dengan hal yang sebenarnya kurang masuk akal dan sangat tidak mengenakkn; Bersandiwara. Pura-pura tak punya rindu, pura-pura tak ada kangen, dan berlagak seakan semuanya baik-baik saja padahal aku tengah menyumbat mulut luka yang mengaga bersama perihnya yang merngaroma… Aku bahkan dengan rasa tega yang penuh meski dengan amat berat hati sudah menutup akses alasanku untuk bisa bertemu dengan dia—you know who—yang sebenernya menjadi muara dari semua rinduku.
Dalam perhitunganku, ketika akses-akses alasan itu sudah aku blokir, aku tak lagi perlu risau menunggu waktu bisa kembalikan masa-masa indah yang pernah melenakanku itu. Aku tak perlu lagi menunggu apakah ada kabar dari masa lalu yang akan kembali melemparkanku pada surga sementaranya. Aku meneguhkan hati—meski sampe sekarang belum teguh-teguh, ehehehehe—bahwa,,,akhir dari episode panjng yang aku jalani haruslah berujung pada keikhlasan…Biarlah ikhlas yang masih mati-matian aku pelajari ini menjadi ikon yang manis dari semua episode yang juga,,,hhh,,,too sweet to forget…Paling tidak, aku harus berpikir ulang SERIBU SERATUS KALI untuk mencabut ucapanku, menjilati lidah yang sudah aku buang, dan membuka jalur akses alasan yang sudah aku dirikan semenjulang mungkin.
Rindu mengajarkan banyak hal, semisal bersyukur atas momen dan anugerah yang sudah berlalu, bagaimana mengikhlaskan banyak hal dan menjadikannya tambang hikmah yang tak akan habis digali, namun rindu ternyata licik juga. Aku merasakan hal ini utamanya dalam hal…apologinya yang terlalu berlebihan. Entah, percaya atau tidak, sudah pernah atau belum pernah kaualami, aku rasa rindu menjadi rezim paling otoriter yang bisa dengan mudah memasukkan ‘intervensi’ seseorang ke dalam semua lini kehidupan. Mudahnya, tak jauh beda dengan salah satu lirik yang dinyanyikan Avril Lavigne, everything that I do, reminds me of youu….Dan lirik itu bukan hanya wacana yang mengawang-ngawang, Saudara-saudara!!!!!!
Aku merasakan, mengalami, dan menyaksikannya sendiri. Meski latar belakang rinduku memang support, namun aku bisa memprediksi bahwa gejala ini tak hanya menjangkitiku. Ya, pernahkah Kau merasakan bahwa ketika Kau merindukan seseorang, dia bisa hadir di setiap tempat yang pijak dan setiap waktu yang kau temui? Pada semua keadaan yang melibatkanmu, pada setiap suasana yang menjadi rutinitasmu, dan semuanya. Di setiap denyut pikiran, di setiap jengkal tempat, di semua perasaan, dan dalam 24 jam sehari serta 7 hari sepekan. Dalam hal ini, mau tidak mau, apologi yang berlebihan menjadi salah satu komponen yang akan mendukung suksesi gejala ketiga ini.
Ngeselin emang, tapi rasa rindu berikut gejala-gejalanya—yang barangkali akan sangat amat berbeda di antara masing-masing orang—adalah suatu hal yang alami an-sich dan amt sangat natural. Jadi, mustahil rasanya untuk bisa menghindar dan berlari. Aku sendiri, hingga hari ini, masih percaya, bahwa rindu akan menemukan bentuk dan riwayatnya sendiri, bersama teka-teki yang akan disingkap oleh sang waktu…
Untuk seseorang yang berada di balik pikiran dan perasaanku ketika menulis ini, aku ingin…ingin sekali mengulang kembali semua momen-momen yang tak akan datang kembali lagi. Momen bersamamu, momen mengenalmu, momen menghujatmu, momen memujamu, momen menghawatirkanmu, dan saat ini, momoen merindukanmu adalah rentetan-rentetan proses yang banyak banget berandil dalam membentuk keseluruhan diriku. Aku sama sekali tak pernah berpikir bahwa…Aku akan merindukanku segila ini, akan menyanyangimu setakterdefinisi ini…
Kalaupun kau pasti tidak akan kembali—karena aku harus selalu memastikan bahwa aku benar-benar pergi dari hidupmu—aku masih menaruh harap di batas putus asaku yang paling dalam, untuk kembali merasakan energi-energi yang sering kaupekikkan di telinga tuliku. Tidak untuk memintamu kembali datang dan bertandang, namun untuk mengabadikan sosok dan kenangan bersamamu dalam memoriku yang tak akan pernah terhapus oleh apapun…
Malam ini, atau mungkin pagi ini, aku kembali rindu pada segenapmu. Rindu pada perdebatan panjang kita yang kebanyakan tak berujung-pangkal, rindu pada diammu yang tak pernah mau aku bobol, rindu pada optimismemu, dan yang pasti, aku rindu caramu mencintaiku dan membuatku tak lagi merasa bahwa engkau adalah orang lain. Aku rindu malam-malam panjang ituuu…Jika saja kau baca tulisan ini, kau mungkin akan tau, aku kembali menangis, untuk dan karenamu. Selamat tidur, lelaplah di hatiku.
*) Written on 09-10-10
Hmhm...
G3 (Gu` gang gu`)
Jumat, 05 November 2010
Kwalik-walik...
Semiotika Ferdinand D. Saussure
Masyithah Mardhatillah (07530003)
A. Pegantar
Secara garis besar, semiotika bisa diartikan sebagai salah satu cabang linguistik yang secara khusus mengkaji tanda yang telah memasyarakat dalam kehidupan manusia. Seorang ahli bahasa kenamaan, Saussure, telah sejak dahulu menyadari bahwa bahasa komunikasi antar sesama manusia ataupun antar manusia dengan lingkungannya tidak hanya terbatas pada tradisi oral saja, akan tetapi juga meliputi tradisi tulisan, gerak tubuh, dan lain sebagainya yang berwujud tanda untuk mengungkapkan suatu maksud tertentu.
Dalam hidup keseharian, dari wilayah paling privat hingga wilayah paling publik sekalipun, kita sangat sering menjumpai tanda-tanda, semisal tanda lalu lintas, rute jalur, petunjuk-petunjuk di tempat umum, dan lain sebagainya. Karena sifatnya yang selalu dinamis dan cenderung berbeda antarkomunitas, maka para ahli bahasa menginisiasi adanya suatu cabang linguistik yang khusus mengkaji persoalan tanda. Salah satu tujuan utama dari disiplin ilmu ini adalah mensistemasi konsep-konsep dan segala hal yang berhubungan dengan tanda agar sebuah tanda tertentu tidak disalahpahami dan bisa menunjukkan maksud yang ingin disampaikan.
Tanda merupakan bagian kehidupan yang memiliki dua mata pisau. Adakalanya, tanda bisa amat sangat membantu manusia (jika manusia benar-benar memahami maksud yang direpresentasikan di balik tanda), atau juga bisa malah menyesatkan manusia (misalnya dalam kasus ketika manusia salah memahami tanda). Sebab itulah tidaklah mengherankan jika seorang tokoh bernama Umberto Eco mendefinisikan semiotika sebagai sebuah disiplin yang mempelajari segala sesuatu yang dapat digunakan untuk berdusta. Objek penelitian semiotika adalah tanda yang sangat rentan untuk disalahpahami. Sebab itulah, disiplin ilmu semiotika menjadi sebuah keniscayaan di tengah kehidupan yang sudah memakai tanda sebagai bagian tak terpisahkan.
B. Biografi Saussure
Ferdinand D. Saussure (1857-1913) adalah ilmuwan yang pertama kali mengenalkan istilah semiotika melalui dikotomi sistem tanda, yakni signifed dan signifier. Pada masa hidupnya, Saussure belum secara sistematis merumuskan konsep-konsep linguistik (termasuk semiotika) yang kemudian mengabadikan namanya ini. Dua tahun setelah Saussure meninggal dunia, dua muridnya berinisiasi untuk mengumpulkan bahan-bahan kuliah yang diberikan Saussure selama mengajar di Universitas Jenewa. Nama Saussure senyatanya melambung tinggi berkat buku yang tidak pernah sengaja ditulisnya tersebut, yakni Course in General Linguistic
Ilmuan yang juga disebut sebagai peletak dasar linguistik modern ini lahir di Jenewa pada 26 November 1857 dari keluarga Prostestan yang beremigrasi dari Perancis menuju Lorraine. Bakat dan ketertarikan Saussure terhadap bahasa sudah tampak sedari ia kecil. Hal ini misalnya terlihat ketika usianya 15 tahun, Saussure muda telah menulis esai “Essai sur les Languanges”. Ia pun kemudian memilih kajian Bahasa sebagai bidang yang ditekuninya ketika menjadi mahasiswa ataupun telah menjadi dosen.
C. Pokok-Pokok Pemikiran Saussure
Saussure memiliki ketertarikan untuk menggagas dasar-dasar semiotika karena ia berpandangan bahwa elemen dasar bahasa adalah tanda-tanda linguistik atau tanda-tanda kebahasaan, yang biasa disebut juga kata-kata. Kata-kata yang sudah menjadi udara dalam kehidupan manusia, bagi Saussure, merupakan tanda-tanda linguistik yang memiliki referen tertentu. Tanda-tanda linguistik yang muncul dalam bentuk kata dan kalimat (baik tradisi tulis. tradisi verbal, maupun dalam bentuk-bentuk lain) masih mungkin disalahpahami. Sebab itulah ia kemudian tergerak untuk menggagas konsep mengenai tanda yang kemudian menjadi pijakan dasar ilmu semiotika.
Dalam masterpiece-nya, Course in General Linguistics, Saussure mendefinisikan semiotika sebagai ilmu yang mempelajari struktur, jenis, tipologi, serta relasi-relasi tanda dalam penggunaannya di dalam masyarakat. Dari definsi tersebut, dapat diketahui bahwa objek material ilmu semiotika adalah tanda. Sedangkan fokus area pembelajaran dalam ilmu semiotika ada tiga, yakni (hakikat) tanda, sistem yang mengaturnya, dan budaya di mana tanda tersebut berada. Bagi Saussure, bahasa bukanlah satu-satunya sistem tanda yang dipakai dalam masyarakat, sebab masih ada sistem tanda lain yang muncul bersama dengan perkembangan zaman, seperti lampu lalu lintas berwarna merah untuk berhenti, hijau untuk jalan terus, gerak tubuh dan isyarat bagi penyandang cacat, dan lain sebagainya.
Bisa jadi, karena pandangannya mengenai tanda yang dinamis ini, Saussure memiliki ketertarikan khusus untuk mengkaji tanda-tanda yang hidup dalam masyarakat. Tanda yang menjadi objek material dalam disiplin semiotika adalah tanda yang memenuhi dua kualifikasi, yakni tanda yang dapat diamati dan tanda yang menunjukkan sesuatu yang lain. Kualifikasi pertama berarti bahwa tanda yang menjadi objek material dalam semiotika adalah tanda yang konkret atau terindra, sedangkan kualifikasi kedua berarti bahwa tanda harus memiliki acuan terhadap sesuatu yang lain (untuk menyampaikan suatu maksud) yang bukan merupakan tanda itu sendiri.
Secara general, pokok-pokok pemikiran Saussure tersaji dalam eksplorasi-eskplorasi yang bersifat dikomotik dan distingtif. Dalam hal ini, ada beberapa pokok kajian yang menjadi titik tekan pembahasan Saussure, di antaranya adalah penanda dan petanda, langange, parole, dan langue, serta metode sinkroni dan diakroni. Dengan tiga konsep—yang ternyata tidak hanya dipakai dalam studi bahasa ini—Saussure ingin mengemukakan bahwa bahasa merupakan sistem yang masing-masing komponennya memiliki keterkaitan dan keterikatan serta saling mempengaruhi. Gagasan inilah yang kemudian membidani lahirnya aliran strukturalisme dalam dunia filsafat.
Konsep distingtif pertama yang ditawarkan Saussure adalah mengenai signified (penanda) dan signifier (petanda). Keduanya merupakan dua unsur yang membentuk tanda. Penanda (signifier) adalah aspek material bahasa, yakni bahasa tulis maupun lisan yang digunakan untuk menggambarkan sebuah benda (bisa berupa suara, huruf, gambar, bentuk, dan gerak). Sedangkan konsep dan penjabaran deskriptif mengenai sebuah benda dikatakan petanda (signifier). Sebagai misal ketika seseorang mengatakan “buku”, maka suara yang memperdengarkan kata “buku” dan didengar oleh orang lain merupakan penanda, sedangkan konsep buku sebagai alat untuk menulis atau bahan bacaan merupakan petanda. Adapun benda yang disebut buku, yang merupakan objek, maka disebut referen.
Bagi Saussure, berkumpulnya penanda dan petanda yang mengarah pada suatu benda tertentu merupakan syarat suatu hal bisa dikatakan tanda. Adanya hubungan antara penanda dan petanda kemudian dinamakan signifikasi yang juga menghasilkan makna. Penanda dan petanda merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi, seperti yang dijelaskan Saussure, hubungan antara penanda dan petanda merupakan hubungan yang arbitrer, dalam artian tidak bisa ditelusuri mengapa sebuah penanda harus memiliki petanda tertentu. Karena bersifat arbitrer (semena-mena, tidak dapat ditelusuri asal-usulnya dengan logika), maka tidak ada alasan yang bisa diberikan mengapa binatang berkaki empat yang biasa digunakan sebagai alat transportasi bisa dinamakan kuda, bukan kambing atau sapi. Meski tidak dapat ditelusuri asal-usulnya, tanda yang arbitrer tersebut tetap bisa dipahami oleh semua orang.
Selain mengenai konsep penanda dan petanda, konsep lain yang digagas Saussure adalah konsep mengenai langange, langue, dan parole. Langange adalah ujaran yang mencakup parole (sisi individu dari pribadi penutur) serta langue (kaidah, tata bahasa, dan gramatikal). Sebagai misal, kata mareriil adalah langange karena memuat dua hal, pertama, kata ini sudah lumrah diucapkan dalam masyarakat, kedua, kata tersebut memiliki keterkaitan dengan kaidah gramatika bahasa, yakni memiliki kendala yang membuatnya tidak memeuhi tata gramatika bahasa bahasa, dalam hal ini EYD. Sebab inilah, Saussure kemudian beranggapan bahwa langange bukan merupakan fakta sosial dan tidak memenuhi prinnsip keutuhan sehingga tidak bisa diteliti.
Sedangkan langue adalah bahasa konvensional yang sesuai dengan EYD dan kaidah kebahasaan, meski secara lebih luas langue ini bisa diartikan dengan sistem tanda (dalam bentuk apapun) yang mengungkapkan gagasan. Berbeda dengan langange, kualifikasi gramatikal bahasa yang terpenuhi dalam langue memungkinkan langue untuk diteliti secara ilmiah (semisal dibandingkan dengan tulisan, abjad tuna rungu, ritus simbolis, dan lain-lain), karena ia merupakan bahasa konvensional yang disepakati secara kolektif serta memenuhi kualifikasi gramatika bahasa (prinsip keutuhan). Mudahnya, langue bisa diartikan sebagai aspek kemasyarakatan bahasa yang mengandung bahasa yang sudah menjadi kesepakatan kolektif dan memenuni tata kaidah kebahasaan.
Komponen ketiga adalah parole yang merupakan aplikasi dari langue. Sama halnya dengan langange, parole adalah konsep yang tidak bisa diteliti secara ilmiah. Parole adalah bahasa sehari-hari serta keseluruhan ujaran yang hidup dalam masyarakat. Jadi, selain kasrena parole tiap masyarakat sangat dimungkinkan akan berbeda (secara bahasa maupun dialek), parole yang merupakan bahasa keseharian masyarkat cenderung tidak memerhatikan unsur-unsur kaidah tata bahasa. Titik tekan fungsional parole adalah agar suatu ujaran bisa dimengerti dan maksud si pembicara bisa tersampaikan, bukan untuk memenuhi kualifikasi gramatika bahasa.
Dari ketiga konsep tadi, tujuan linguistik adalah mencari sistem bahasa (langue) dari kenyataan yang konkret (parole). Hal inilah yang sebenarnya menjadi dasar pendekatan strukturalis, yakni tatanan wujud yang mencakup keutuhan, sebuah tatanan yang tidak sekadar merupakan kumpulan beberapa kata, akan tetapi sistem yang tiap komponen di dalamnya tunduk pada kaidah-kaidah intrinsik dan tidak memiliki kebebasan di luar struktur. Sebagai contoh, kalimat saya pergi adalah kalimat yang memenhi konsep langue dan parole. Kalimat tersebut sudah sering diucapkan dan tidak menyalahi tata kaidah kebahasaan. Akan tetapi, ketika kalimat tersebut dibalik menjadi pergi saya, maka kalimat kedua ini akan terasa janggal, karena tidak biasa diucapkan dan menyalahi tata gramatika bahasa.
Konsep ketiga yang disajikan dalam bentuk distingtif oleh Saussure adalah konsep mengenai sinkronik-diakronik. Dua konsep ini mutlak harus dieksplorasi sebab dalam pandangan Saussure, pendekatan sinkronik harus didahulukan dibanding pendekatan diakronik. Pendekatan diakronik adalah analisis tentang perubahan historis bahasa, yakni proses evolusi makna dalam berbagai periode waktu serta perkembangan dan perubahannya. Sedangkan pendekatan sinkronik adalah pendekatan bahasa pada satu momen waktu tertentu saja. Analisis yang juga disebut dengan pendekatan strukturalisme ini menginginkan adanya pendekatan yang hanya melihat struktur bahasa ansich tanpa harus memerhatikan konteks waktu, perubahan, dan sejarahnya.
Jika demikian, maka sangat jelas bahwa Saussure menginginkan adanya pendekatan kebahasaan yang diawali dengan pendekatan kebahasaan ansich tanpa harus terjebak dalam penelusuran sejarah makna sebuah kata. Saussure ingin memetakan sebuah sistem bahasa pada suatu momen tertentu saja dan bukan menelusuri sejarah evolusi makna yang melewati beberapa episode waktu.
Adapun mengenai hubungan tanda, maka Saussure menjelaskan bahwa ada tiga hubungan tanda, yakni simbolik, paradigmatik, dan sintagmatik. Hubungan simbolik adalah hubungan internal antara tanda dengan dirinya sendiri. Sedangkan dua hubungan lainnya, yakni paradigmatik dan sintagmatik adalah hubungan eksternal. Bedanya, paradigmatik adalah hubungan sebuah tanda dengan tanda lain dalam suatu sistem atau kelas, sedangkan hubungan sintagmatik adalah hubungan tanda dengan tanda lain dari sebuah struktur.
Mudahnya, hubungan sintagmatik mencoba mengetahui hubungan satu kata dengan kata yang mengiringinya atau bahkan satu huruf dengan kata yang mengiringinya. Sebagai misal, dalam kalimat the old man, maka untuk meneliti kata old, peneliti bisa merujuk pada kata the atau man. Seperti halnya untuk meneliti huruf m, maka harus juga mengkaji huruf a dan n dalam kata man. Adapun hubungan paradigmatic adalah meneliti suatu kata tertenti dengan melakukan perbandingan pada kata yang sepadan maupun kata yang berlawanan. Sebagai contoh, ketika meneliti the old man, kata peneliti bisa memulainya dengan juga mengkaji the young man, the young woman, dan lain sebagainya. Allah Knows Best
Masyithah Mardhatillah (07530003)
A. Pegantar
Secara garis besar, semiotika bisa diartikan sebagai salah satu cabang linguistik yang secara khusus mengkaji tanda yang telah memasyarakat dalam kehidupan manusia. Seorang ahli bahasa kenamaan, Saussure, telah sejak dahulu menyadari bahwa bahasa komunikasi antar sesama manusia ataupun antar manusia dengan lingkungannya tidak hanya terbatas pada tradisi oral saja, akan tetapi juga meliputi tradisi tulisan, gerak tubuh, dan lain sebagainya yang berwujud tanda untuk mengungkapkan suatu maksud tertentu.
Dalam hidup keseharian, dari wilayah paling privat hingga wilayah paling publik sekalipun, kita sangat sering menjumpai tanda-tanda, semisal tanda lalu lintas, rute jalur, petunjuk-petunjuk di tempat umum, dan lain sebagainya. Karena sifatnya yang selalu dinamis dan cenderung berbeda antarkomunitas, maka para ahli bahasa menginisiasi adanya suatu cabang linguistik yang khusus mengkaji persoalan tanda. Salah satu tujuan utama dari disiplin ilmu ini adalah mensistemasi konsep-konsep dan segala hal yang berhubungan dengan tanda agar sebuah tanda tertentu tidak disalahpahami dan bisa menunjukkan maksud yang ingin disampaikan.
Tanda merupakan bagian kehidupan yang memiliki dua mata pisau. Adakalanya, tanda bisa amat sangat membantu manusia (jika manusia benar-benar memahami maksud yang direpresentasikan di balik tanda), atau juga bisa malah menyesatkan manusia (misalnya dalam kasus ketika manusia salah memahami tanda). Sebab itulah tidaklah mengherankan jika seorang tokoh bernama Umberto Eco mendefinisikan semiotika sebagai sebuah disiplin yang mempelajari segala sesuatu yang dapat digunakan untuk berdusta. Objek penelitian semiotika adalah tanda yang sangat rentan untuk disalahpahami. Sebab itulah, disiplin ilmu semiotika menjadi sebuah keniscayaan di tengah kehidupan yang sudah memakai tanda sebagai bagian tak terpisahkan.
B. Biografi Saussure
Ferdinand D. Saussure (1857-1913) adalah ilmuwan yang pertama kali mengenalkan istilah semiotika melalui dikotomi sistem tanda, yakni signifed dan signifier. Pada masa hidupnya, Saussure belum secara sistematis merumuskan konsep-konsep linguistik (termasuk semiotika) yang kemudian mengabadikan namanya ini. Dua tahun setelah Saussure meninggal dunia, dua muridnya berinisiasi untuk mengumpulkan bahan-bahan kuliah yang diberikan Saussure selama mengajar di Universitas Jenewa. Nama Saussure senyatanya melambung tinggi berkat buku yang tidak pernah sengaja ditulisnya tersebut, yakni Course in General Linguistic
Ilmuan yang juga disebut sebagai peletak dasar linguistik modern ini lahir di Jenewa pada 26 November 1857 dari keluarga Prostestan yang beremigrasi dari Perancis menuju Lorraine. Bakat dan ketertarikan Saussure terhadap bahasa sudah tampak sedari ia kecil. Hal ini misalnya terlihat ketika usianya 15 tahun, Saussure muda telah menulis esai “Essai sur les Languanges”. Ia pun kemudian memilih kajian Bahasa sebagai bidang yang ditekuninya ketika menjadi mahasiswa ataupun telah menjadi dosen.
C. Pokok-Pokok Pemikiran Saussure
Saussure memiliki ketertarikan untuk menggagas dasar-dasar semiotika karena ia berpandangan bahwa elemen dasar bahasa adalah tanda-tanda linguistik atau tanda-tanda kebahasaan, yang biasa disebut juga kata-kata. Kata-kata yang sudah menjadi udara dalam kehidupan manusia, bagi Saussure, merupakan tanda-tanda linguistik yang memiliki referen tertentu. Tanda-tanda linguistik yang muncul dalam bentuk kata dan kalimat (baik tradisi tulis. tradisi verbal, maupun dalam bentuk-bentuk lain) masih mungkin disalahpahami. Sebab itulah ia kemudian tergerak untuk menggagas konsep mengenai tanda yang kemudian menjadi pijakan dasar ilmu semiotika.
Dalam masterpiece-nya, Course in General Linguistics, Saussure mendefinisikan semiotika sebagai ilmu yang mempelajari struktur, jenis, tipologi, serta relasi-relasi tanda dalam penggunaannya di dalam masyarakat. Dari definsi tersebut, dapat diketahui bahwa objek material ilmu semiotika adalah tanda. Sedangkan fokus area pembelajaran dalam ilmu semiotika ada tiga, yakni (hakikat) tanda, sistem yang mengaturnya, dan budaya di mana tanda tersebut berada. Bagi Saussure, bahasa bukanlah satu-satunya sistem tanda yang dipakai dalam masyarakat, sebab masih ada sistem tanda lain yang muncul bersama dengan perkembangan zaman, seperti lampu lalu lintas berwarna merah untuk berhenti, hijau untuk jalan terus, gerak tubuh dan isyarat bagi penyandang cacat, dan lain sebagainya.
Bisa jadi, karena pandangannya mengenai tanda yang dinamis ini, Saussure memiliki ketertarikan khusus untuk mengkaji tanda-tanda yang hidup dalam masyarakat. Tanda yang menjadi objek material dalam disiplin semiotika adalah tanda yang memenuhi dua kualifikasi, yakni tanda yang dapat diamati dan tanda yang menunjukkan sesuatu yang lain. Kualifikasi pertama berarti bahwa tanda yang menjadi objek material dalam semiotika adalah tanda yang konkret atau terindra, sedangkan kualifikasi kedua berarti bahwa tanda harus memiliki acuan terhadap sesuatu yang lain (untuk menyampaikan suatu maksud) yang bukan merupakan tanda itu sendiri.
Secara general, pokok-pokok pemikiran Saussure tersaji dalam eksplorasi-eskplorasi yang bersifat dikomotik dan distingtif. Dalam hal ini, ada beberapa pokok kajian yang menjadi titik tekan pembahasan Saussure, di antaranya adalah penanda dan petanda, langange, parole, dan langue, serta metode sinkroni dan diakroni. Dengan tiga konsep—yang ternyata tidak hanya dipakai dalam studi bahasa ini—Saussure ingin mengemukakan bahwa bahasa merupakan sistem yang masing-masing komponennya memiliki keterkaitan dan keterikatan serta saling mempengaruhi. Gagasan inilah yang kemudian membidani lahirnya aliran strukturalisme dalam dunia filsafat.
Konsep distingtif pertama yang ditawarkan Saussure adalah mengenai signified (penanda) dan signifier (petanda). Keduanya merupakan dua unsur yang membentuk tanda. Penanda (signifier) adalah aspek material bahasa, yakni bahasa tulis maupun lisan yang digunakan untuk menggambarkan sebuah benda (bisa berupa suara, huruf, gambar, bentuk, dan gerak). Sedangkan konsep dan penjabaran deskriptif mengenai sebuah benda dikatakan petanda (signifier). Sebagai misal ketika seseorang mengatakan “buku”, maka suara yang memperdengarkan kata “buku” dan didengar oleh orang lain merupakan penanda, sedangkan konsep buku sebagai alat untuk menulis atau bahan bacaan merupakan petanda. Adapun benda yang disebut buku, yang merupakan objek, maka disebut referen.
Bagi Saussure, berkumpulnya penanda dan petanda yang mengarah pada suatu benda tertentu merupakan syarat suatu hal bisa dikatakan tanda. Adanya hubungan antara penanda dan petanda kemudian dinamakan signifikasi yang juga menghasilkan makna. Penanda dan petanda merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi, seperti yang dijelaskan Saussure, hubungan antara penanda dan petanda merupakan hubungan yang arbitrer, dalam artian tidak bisa ditelusuri mengapa sebuah penanda harus memiliki petanda tertentu. Karena bersifat arbitrer (semena-mena, tidak dapat ditelusuri asal-usulnya dengan logika), maka tidak ada alasan yang bisa diberikan mengapa binatang berkaki empat yang biasa digunakan sebagai alat transportasi bisa dinamakan kuda, bukan kambing atau sapi. Meski tidak dapat ditelusuri asal-usulnya, tanda yang arbitrer tersebut tetap bisa dipahami oleh semua orang.
Selain mengenai konsep penanda dan petanda, konsep lain yang digagas Saussure adalah konsep mengenai langange, langue, dan parole. Langange adalah ujaran yang mencakup parole (sisi individu dari pribadi penutur) serta langue (kaidah, tata bahasa, dan gramatikal). Sebagai misal, kata mareriil adalah langange karena memuat dua hal, pertama, kata ini sudah lumrah diucapkan dalam masyarakat, kedua, kata tersebut memiliki keterkaitan dengan kaidah gramatika bahasa, yakni memiliki kendala yang membuatnya tidak memeuhi tata gramatika bahasa bahasa, dalam hal ini EYD. Sebab inilah, Saussure kemudian beranggapan bahwa langange bukan merupakan fakta sosial dan tidak memenuhi prinnsip keutuhan sehingga tidak bisa diteliti.
Sedangkan langue adalah bahasa konvensional yang sesuai dengan EYD dan kaidah kebahasaan, meski secara lebih luas langue ini bisa diartikan dengan sistem tanda (dalam bentuk apapun) yang mengungkapkan gagasan. Berbeda dengan langange, kualifikasi gramatikal bahasa yang terpenuhi dalam langue memungkinkan langue untuk diteliti secara ilmiah (semisal dibandingkan dengan tulisan, abjad tuna rungu, ritus simbolis, dan lain-lain), karena ia merupakan bahasa konvensional yang disepakati secara kolektif serta memenuhi kualifikasi gramatika bahasa (prinsip keutuhan). Mudahnya, langue bisa diartikan sebagai aspek kemasyarakatan bahasa yang mengandung bahasa yang sudah menjadi kesepakatan kolektif dan memenuni tata kaidah kebahasaan.
Komponen ketiga adalah parole yang merupakan aplikasi dari langue. Sama halnya dengan langange, parole adalah konsep yang tidak bisa diteliti secara ilmiah. Parole adalah bahasa sehari-hari serta keseluruhan ujaran yang hidup dalam masyarakat. Jadi, selain kasrena parole tiap masyarakat sangat dimungkinkan akan berbeda (secara bahasa maupun dialek), parole yang merupakan bahasa keseharian masyarkat cenderung tidak memerhatikan unsur-unsur kaidah tata bahasa. Titik tekan fungsional parole adalah agar suatu ujaran bisa dimengerti dan maksud si pembicara bisa tersampaikan, bukan untuk memenuhi kualifikasi gramatika bahasa.
Dari ketiga konsep tadi, tujuan linguistik adalah mencari sistem bahasa (langue) dari kenyataan yang konkret (parole). Hal inilah yang sebenarnya menjadi dasar pendekatan strukturalis, yakni tatanan wujud yang mencakup keutuhan, sebuah tatanan yang tidak sekadar merupakan kumpulan beberapa kata, akan tetapi sistem yang tiap komponen di dalamnya tunduk pada kaidah-kaidah intrinsik dan tidak memiliki kebebasan di luar struktur. Sebagai contoh, kalimat saya pergi adalah kalimat yang memenhi konsep langue dan parole. Kalimat tersebut sudah sering diucapkan dan tidak menyalahi tata kaidah kebahasaan. Akan tetapi, ketika kalimat tersebut dibalik menjadi pergi saya, maka kalimat kedua ini akan terasa janggal, karena tidak biasa diucapkan dan menyalahi tata gramatika bahasa.
Konsep ketiga yang disajikan dalam bentuk distingtif oleh Saussure adalah konsep mengenai sinkronik-diakronik. Dua konsep ini mutlak harus dieksplorasi sebab dalam pandangan Saussure, pendekatan sinkronik harus didahulukan dibanding pendekatan diakronik. Pendekatan diakronik adalah analisis tentang perubahan historis bahasa, yakni proses evolusi makna dalam berbagai periode waktu serta perkembangan dan perubahannya. Sedangkan pendekatan sinkronik adalah pendekatan bahasa pada satu momen waktu tertentu saja. Analisis yang juga disebut dengan pendekatan strukturalisme ini menginginkan adanya pendekatan yang hanya melihat struktur bahasa ansich tanpa harus memerhatikan konteks waktu, perubahan, dan sejarahnya.
Jika demikian, maka sangat jelas bahwa Saussure menginginkan adanya pendekatan kebahasaan yang diawali dengan pendekatan kebahasaan ansich tanpa harus terjebak dalam penelusuran sejarah makna sebuah kata. Saussure ingin memetakan sebuah sistem bahasa pada suatu momen tertentu saja dan bukan menelusuri sejarah evolusi makna yang melewati beberapa episode waktu.
Adapun mengenai hubungan tanda, maka Saussure menjelaskan bahwa ada tiga hubungan tanda, yakni simbolik, paradigmatik, dan sintagmatik. Hubungan simbolik adalah hubungan internal antara tanda dengan dirinya sendiri. Sedangkan dua hubungan lainnya, yakni paradigmatik dan sintagmatik adalah hubungan eksternal. Bedanya, paradigmatik adalah hubungan sebuah tanda dengan tanda lain dalam suatu sistem atau kelas, sedangkan hubungan sintagmatik adalah hubungan tanda dengan tanda lain dari sebuah struktur.
Mudahnya, hubungan sintagmatik mencoba mengetahui hubungan satu kata dengan kata yang mengiringinya atau bahkan satu huruf dengan kata yang mengiringinya. Sebagai misal, dalam kalimat the old man, maka untuk meneliti kata old, peneliti bisa merujuk pada kata the atau man. Seperti halnya untuk meneliti huruf m, maka harus juga mengkaji huruf a dan n dalam kata man. Adapun hubungan paradigmatic adalah meneliti suatu kata tertenti dengan melakukan perbandingan pada kata yang sepadan maupun kata yang berlawanan. Sebagai contoh, ketika meneliti the old man, kata peneliti bisa memulainya dengan juga mengkaji the young man, the young woman, dan lain sebagainya. Allah Knows Best
Hmhm...
TugaZ dari doZhen